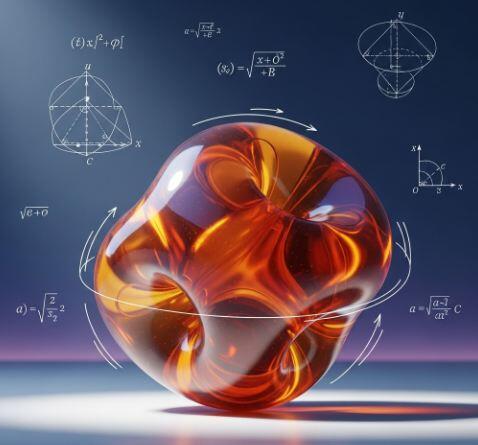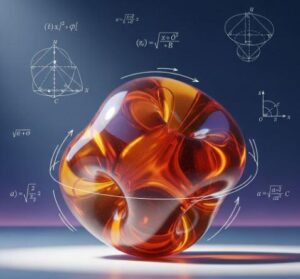Suara Alam Kena Royalti saat Rekaman Dijual, Siapa Pemilik Hak Paten dari Suara Alam?
Bayangkan Anda sedang duduk santai di sebuah kafe pinggir hutan. Sinar mentari sore menembus sela-sela dedaunan, aroma kopi menyeruak, & di kejauhan terdengar suara kicau burung merdu yg seolah jadi iringan musik alami. Bagi telinga, itu adalah hiburan gratis dari alam. Bagi hati, itu adalah terapi. Namun, di balik kenyamanan itu, muncul pertanyaan yg unik: Apakah suara alam seperti ini memiliki hak cipta? Apakah seseorang harus membayar royalti untuk menikmatinya?
disadur oleh Kibul Gonzales
Suara Alam: Gratis atau Berbayar?
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) baru-baru ini memberikan penjelasan resmi yg cukup menarik perhatian. Menurut Komisioner Bidang Lisensi & Kolekting LMKN, Jhonny W. Maukar, suara burung atau suara alam yg didengar langsung tanpa perekaman tidak dikenakan royalti. Dengan mengatakan lain, selama Anda mendengarnya langsung dari sumbernya misalnya burung di sangkar atau gemericik air sungai itu sepenuhnya gratis & bebas dipakai.
Namun, ceritanya berubah ketika suara itu direkam & diputar ulang. Begitu ada proses perekaman atau yg dalam istilah hukum disebut fiksasi, hak cipta berlaku. Dalam konteks hukum hak cipta, fiksasiberarti mengikat atau merekam sebuah karya ke dalam bentuk yg dapat dilihat atau didengar kembali. Artinya, ketika kicau burung tersebut jadi file audio yg dapat diputar berulang-ulang, ia sudah masuk ke ranah proteksi hukum.
Siapa Pemilik Hak dari Suara Alam yg Direkam?
Ini bagian yg sering disalahpahami. Banyak orang mungkin berpikir bahwa pemilik suara alam adalah “alam” itu sendiri atau bahkan hewan yg mengeluarkannya. Tetapi, hukum tidak bekerja seperti itu. Dalam kasus ini, pemilik hak bukan burungnya & jelas bukan hutan yg menghasilkan suara tersebut. Pemegang hak justru adalah produser fonogram atau pihak yg mengerjakan perekaman.
Jika yg merekam adalah seorang pemilik kafe, maka dia lah yg berhak atas rekaman itu. Menariknya, kalau pemilik kafe tersebut terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dia juga dapat mendapatkan kembali beberapa akbar royalti yg dibayarkan orang lain untuk mengpakai rekaman tersebut. Menurut LMKN, 80 persen royalti akan dikembalikan kepada pemegang hak, sementara 20 persen sisanya dipakai untuk biaya operasional.
Bagaimana Jika Pemilik Kafe Ingin Menghindari Royalti Penuh?
Jhonny W. Maukar menyarankan langkah cerdas: rekam sendiri suara yg harap dipakai. Misalnya, kalau sebuah kafe harap memiliki latar suara hutan hujan tropis, mereka dapat pergi ke hutan, mengerjakan perekaman, mendaftarkannya, & mengpakainya secara legal tanpa harus membayar royalti kepada pihak lain. Bahkan, mereka dapat mendapatkan royalti kalau pihak lain harap mengpakai rekaman tersebut.
Dengan cara ini, pemilik kafe tidak cuma mendapatkan suasana yg unik, tetapi juga menciptakan aset intelektual yg dapat menghasilkan pendapatan tambahan.
Perspektif dari LMK Selmi
Hal senada juga diungkapkan oleh Jusak Irwan Setiono, Ketua LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (Selmi). Ia menegaskan bahwa suara alam yg asli atau langsung tanpa rekaman, memang tidak memiliki pencipta ataupun produser fonogram. Artinya, tidak ada dasar untuk mengenakan royalti.
Namun, situasinya berbeda kalau ada proses perekaman. Jusak memberi contoh: kalau seseorang dengan sengaja pergi ke hutan, menunggu burung berkicau, lalu merekamnya, proses itu melibatkan usaha, waktu, bahkan biaya. Karena itu, si perekam memiliki hak sebagai produser fonogram.
Pembagian Royalti
Dalam industri musik & rekaman, royalti biasanya dibagi ke tiga pihak utama:
[ol][li]Pencipta orang yg menciptakan komposisi musik atau lirik.[/li][li]Pelaku pertunjukan orang yg membawakan karya tersebut (penyanyi, musisi, narator, dll.).[/li][li]Produser fonogram pihak yg merekam & memproduksi karya tersebut.[/li][/ol]
Nah, dalam konteks suara alam, umumnya tidak ada pencipta atau pelaku pertunjukan. Burung berkicau bukanlah “pencipta” dalam arti hukum, & ia tidak dianggap mengerjakan “pertunjukan” yg dilindungi. Maka, royalti yg berlaku cuma untuk hak terkait milik produser fonogram.
Misalnya, untuk sebuah kafe dengan kapasitas 50 kursi, LMK dapat menetapkan royalti sekitar Rp 120 ribu per kursi per tahun. Jika suara yg dipakai adalah musik ciptaan manusia, royalti dibagi dua: Rp 60 ribu untuk hak cipta, & Rp 60 ribu untuk hak terkait. Tetapi, kalau yg dipakai cuma rekaman suara alam, maka cuma Rp 60 ribu yg dihitung untuk hak terkait.
Tujuan di Balik Kebijakan Ini
Jusak Irwan Setiono menekankan bahwa penarikan royalti bukanlah aksi sepihak. Prinsipnya adalah keberlanjutan ekosistem. Jika para pelaku usaha ditekan dengan biaya berlebihan, mereka dapat gulung tikar, yg pada akhirnya merugikan semua pihak, termasuk LMK & LMKN. Tujuannya adalah supaya produser fonogram tetap mendapatkan apresiasi atas karya rekamannya, tanpa membebani pengguna secara tidak wajar.
Apakah Suara Alam Bisa Dipatenkan?
Pertanyaan ini membawa kita ke ranah yg sedikit berbeda: hak cipta & hak paten adalah dua hal yg tidak sama. Hak cipta melindungi ekspresi ide dalam bentuk karya, seperti musik, film, foto, & rekaman audio. Sementara hak paten melindungi penemuan atau perkembangan teknis.
Suara alam, dalam bentuk aslinya, tidak dapat dipatenkan karena bukan hasil ciptaan manusia & bukan penemuan teknis. Namun, hasil perekaman suara alam dapat dilindungi hak cipta sebagai fonogram. Jadi, tidak ada “pemilik paten suara burung” dalam hukum, tetapi ada pemegang hak cipta rekaman suara burung.
Sebagai contoh:
[ul][li]Tidak dapat dipatenkan: Suara asli burung jalak di alam liar.[/li][li]Bisa dilindungi hak cipta: File rekaman audio burung jalak yg direkam oleh seorang profesional.[/li][/ul]
Peluang Bisnis dari Rekaman Suara Alam
Fenomena ini membuka peluang bisnis baru. Para pembuat konten, pemilik kafe, hingga platform streaming dapat memanfaatkan rekaman suara alam sebagai aset bernilai. Di era digital, banyak orang yg mencari suara alam untuk meditasi, relaksasi, atau latar belakang kerja (ambient sound).
Bayangkan seorang pehobi alam pergi ke hutan Kalimantan, merekam suara hujan deras bercampur kicauan burung enggang, lalu menjual lisensinya di platform musik atau aplikasi meditasi. Setiap kali rekaman itu dipakai, ia berhak mendapatkan royalti sebagai produser fonogram.
Bahkan, di beberapa negara, ada perusahaan yg spesifik memproduksi & menjual library suara alam. Perpustakaan audio ini dipakai oleh pembuat film, pengembang game, hingga pengelola hotel & spa. Dengan regulasi LMKN, model bisnis seperti ini juga dapat berkembang di Indonesia.
Risiko & Etika
Meski secara hukum produser fonogram berhak atas rekaman suara alam, ada aspek etika yg perlu diperhatikan. Misalnya, kalau perekaman dilakukan di wilayah konservasi atau melibatkan spesies langka, izin dari pihak berwenang jadi wajib. Selain itu, penggunaan suara alam untuk tujuan komersial harus mempertimbangkan akibat kepada satwa & ekosistem.
Misalnya, memasang speaker dengan volume tinggi di dekat habitat burung liar demi “menarik pengunjung” dapat mengganggu perilaku satwa tersebut. Di sini, regulasi lingkungan hidup dapat berperan, meski berbeda dari hukum hak cipta.
Jadi, suara alam asli yg kita dengar langsung tidak pernah dikenakan royalti, karena tidak ada proses perekaman & tidak ada pihak yg memegang hak cipta. Namun, begitu suara itu direkam, ia berubah jadi karya fonogram yg memiliki proteksi hukum. Pemegang haknya adalah pihak yg mengerjakan perekaman, bukan alam atau satwanya.
Bagi pelaku usaha, ada dua pilihan:
[ol][li]Membayar royalti untuk rekaman milik orang lain.[/li][li]Merekam sendiri & jadi pemilik hak, sehingga dapat mengpakainya bahkan mendapatkan royalti dari pihak lain.[/li][/ol]Di tengah tren kebutuhan audio unik untuk berbagai keperluan, pemahaman tentang aturan ini dapat jadi kunci untuk memanfaatkan suara alam secara kreatif, legal, & berkelanjutan.
disadur oleh Kibul Gonzales