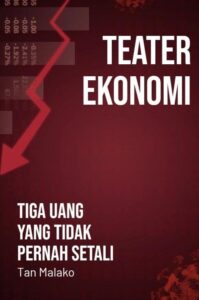Resensi Film Dogtooth (2009): Dunia yg Dikurung dalam Bahasa
Ada dunia(world)sebelum kata(word), dunia di mana kita tidak punya bayangan sama sekali tentangnya, tetapi kita tak pernah tinggal di sana. Kita lahir, dibungkus nama, & langsung ditenggelamkan ke dalam sistem simbol. Dogtooth (2009), film karya Yorgos Lanthimos yg dibintangi oleh Christos Stergioglou, Michelle Valley, Angeliki Papoulia, Mary Tsoni, & Christos Passalis, memperlihatkan kepada kita apa yg terjadi bila satu keluarga menciptakan ulang dunia dari nol—dengan bahasa sebagai alat sekaligus pagar.
Tiga anak dibesarkan tanpa akses ke luar rumah, tanpa televisi, tanpa konsep dunia luar, & lebih mengerikannya: tanpa makna yg disepakati secara universal. Di dunia mereka, “laut” berarti kursi, “telepon” adalah garam, & “zombie” adalah kembang kecil. Setiap mengatakan sudah diganti definisinya oleh sang ayah, & tak seorang pun dapat menolak. Mereka tidak tahu bahwa kata-kata itu dapat berarti lain, karena mereka tidak tahu bahwa dunia lain itu ada.
Di sinilah kekuasaanDogtoothbekerja: dalam diam, dalam kamus yg dipalsukan. Ketika orang bertanya, “mengapa mereka tidak kabur?”, jawabannya adalah: kabur ke mana? Apa itu “kabur”? Apa itu “ke luar”? Mereka tidak punya mengatakan untuk membayangkan kebebasan.
Yorgos Lanthimos tidak menggambarkan sang ayah sebagai tiran yg bengis. Ia bukan monster dalam arti konvensional. Christos Stergioglou memainkannya sebagai pria tenang, penyayang dalam versinya, & sangat yakin bahwa ia melindungi anak-anaknya dari kekotoran dunia. Tapi justru di situlah letak kekerasannya: ia tak cuma mengunci pintu, tetapi juga mengunci makna. Dan begitu makna dikunci, realitas berhenti berkembang.
Angeliki Papoulia & Mary Tsoni memerankan dua anak perempuan yg hidup dalam rutinitas absurditas domestik: menari, berenang, belajar kata-kata palsu, & menerima kehadiran seorang wanita dari luar (dengan mata ditutup) yg didatangkan cuma untuk kebutuhan seksual sang anak lelaki. Dunia mereka stabil, steril, & tak terganggu—sebuah simulasi utopia yg sebenarnya distopia linguistik.
Dogtoothbukan film horor, tetapi terasa seperti mimpi buruk bagi siapa saja yg pernah percaya bahwa dunia dapat ditafsirkan secara bebas. Dunia dalam film ini bukan tempat; ia adalah sistem pengertian. Dunia tidak runtuh karena perang, tetapi karena tidak ada mengatakan yg cukup untuk menunjuk kenyataan. Dalam semestaDogtooth, kebebasan bukan direnggut—ia bahkan belum sempat ditemukan.
Namun film ini tidak sepenuhnya asing. Ia justru terasa sangat dekat. Bukankah kita juga dibesarkan dalam sistem bahasa yg sudah siap pakai? Kita diberi nama sebelum dapat memilih, diberi Tuhan sebelum dapat bertanya, diberi bendera sebelum dapat membaca. Kita menyerap dunia melalui kata-kata yg diwariskan, & jarang punya kesempatan untuk menguji apakah dunia itu sungguh milik kita.
Yorgos Lanthimos mengpakai kamera statis & dialog datar untuk menciptakan rasa asing yg tenang, seolah memperlihatkan bahwa ini bukan kegilaan, tetapi ketertiban yg salah. Tidak ada kekerasan visual yg eksplisit, tetapi kekerasan simbolik meresap ke setiap adegan. Ketika seorang anak memukul giginya sendiri hingga copot—karena percaya bahwa itu syarat untuk keluar rumah—kita menyadari bahwa luka paling dalam bukan di tubuh, tetapi di struktur makna.
Judul film ini,Dogtooth, sendiri adalah lelucon sinis: gigi anjing yg katanya harus copot supaya seseorang dapat keluar rumah. Tentu saja tidak ada dasar biologis untuk itu. Tapi itu bukan soal kebenaran, melainkan kredo. Dalam dunia tertutup, kredo dapat jadi kebenaran mutlak. Dan untuk keluar dari kredo, seseorang harus melukai dirinya lebih dulu. Haruskah semua pelarian dimulai dengan pengorbanan?
Michelle Valley, sebagai sang ibu, memperkuat absurditas rumah ini dengan kehadiran yg hampir transparan. Ia tidak menindas, tetapi juga tidak melindungi. Ia diam bukan karena tidak tahu, tetapi karena ia sendiri sudah jadi bagian dari dunia yg dikondisikan.Dogtoothmenunjukkan bahwa pelaku kekerasan simbolik tidak harus sadar diri—bahkan dapat jadi mereka percaya bahwa mereka sedang mensayangi.
Apa yg dihinggakan film ini bukan cuma tentang keluarga, tetapi tentang kita semua: tentang bagaimana dunia adalah kesepakatan yg diturunkan, bukan kenyataan yg ditemukan. Dunia adalah konsensus linguistik yg diulang-ulang hingga terasa alamiah. Dalam duniaDogtooth, dunia itu tidak pernah datang. Yang ada cuma tiruan dunia, versi kecil yg dikontrol penuh oleh otoritas tunggal.
Film ini dapat dibaca sebagai alegori tentang negara, agama, sistem pendidikan, bahkan media. Semua institusi itu memiliki kekuatan untuk mengatur apa yg boleh dikatakan & apa yg dianggap “tidak masuk akal”. TapiDogtoothmenghindari khotbah. Ia tidak menyodorkan argumen, melainkan menciptakan ruang kontemplasi lewat absurditas yg menyakitkan. Kita tidak disuruh membenci, cuma diajak untuk menoleh ke rumah masing-masing & bertanya: siapa yg perdana kali mengajariku arti dunia?
Dan mungkin, pada akhirnya, kita menyadari bahwa kita juga sedang mencoba mencabut gigi taring itu—diam-diam, dalam doa, dalam tulisan, dalam mimpi yg belum sempat kita artikulasikan. Sebab, di luar pagar bahasa yg kita kenal, mungkin masih ada dunia lain yg belum disebutkan namanya.
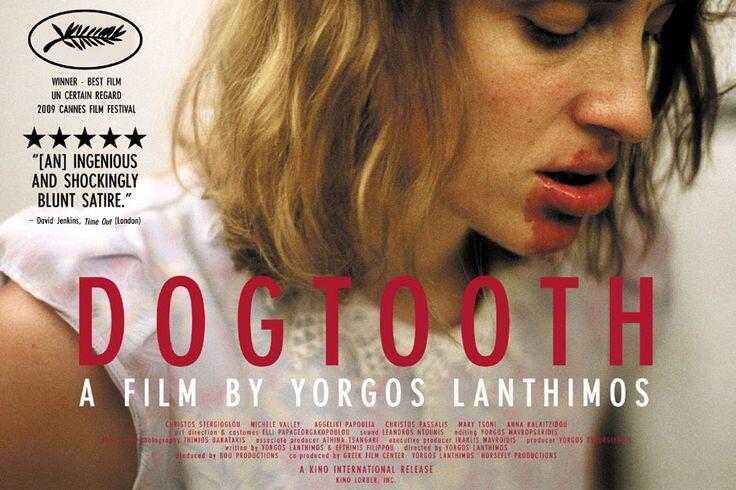


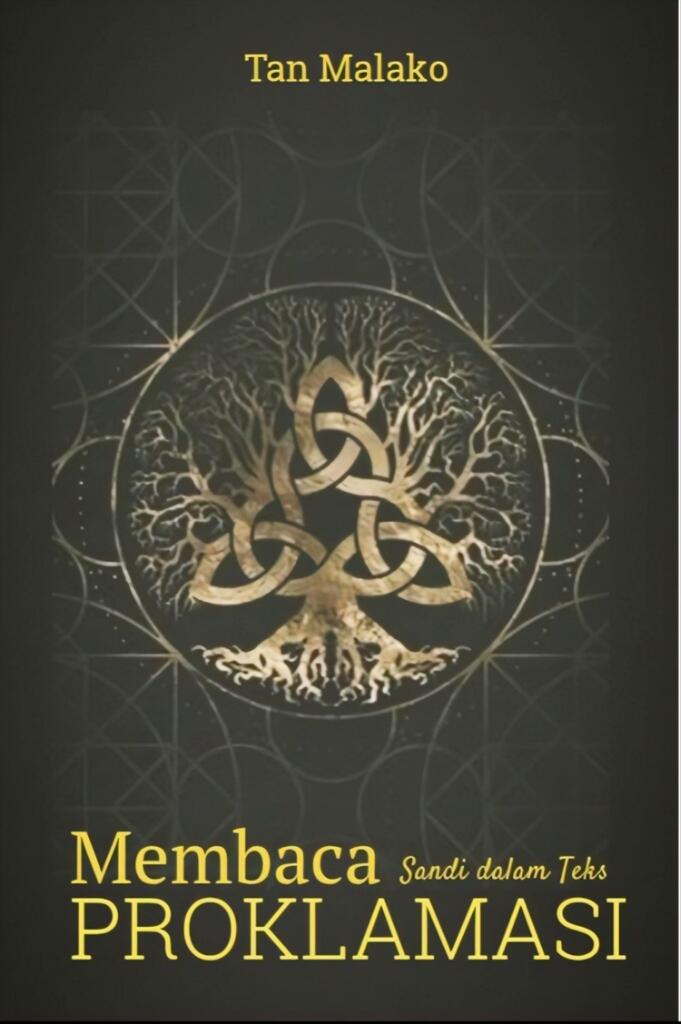



![[HOT ISSUE] Pajak Tanah Naik 4001000%, Warga Menjerit!](https://wgnewss.com/wp-content/themes/newscrunch/assets/images/no-preview.jpg)