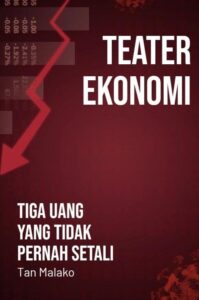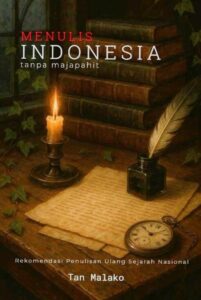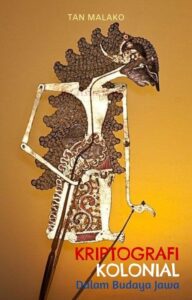Rekonstruksi Sejarah Pesantren: Benteng Tradisi atau Warisan Misionaris Kolonia?
Pesantren selama ini dielu-elukan sebagai salah satu benteng terakhir peradaban Islam di Nusantara. Dalam buku-buku sejarah yg diajarkan di sekolah, ia kerap dipotret sebagai mercusuar keilmuan, tempat lahirnya ulama kharismatik, pusat perlawanan kepada kolonialisme, sekaligus wadah pembentukan moral bangsa. Narasi itu nyaris tanpa cela. Ia diulang terus, dari buku pelajaran hingga mimbar khutbah, seakan tidak ada ruang untuk keraguan.
Tetapi, sejarah sering menyisakan ruang bagi pertanyaan yg tidak nyaman. Apakah benar pesantren lahir murni dari rahim tradisi Islam lokal? Apakah ia betul-betul merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan para ulama terdahulu, bebas dari infiltrasi ideologis kekuatan asing? Atau, justru sejak awal, pesantren sudah dibentuk oleh kekuatan politik yg bekerja di balik layar, dengan agenda kolonial yg tak pernah diakui?
Pertanyaan semacam ini jarang sekali diajukan, apalagi dijawab. Sejarah arus utama kita jarang menyentuh sisi gelap institusi ini. Kita cenderung menerima begitu saja bahwa pesantren adalah warisan asli, lahir dari tradisi Islam yg menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Kita diajari bahwa ia merupakan kelanjutan alami dari pengajaran di surau atau masjid pada masa Walisongo. Namun, kalau kita menggeser sudut pandang, menelusuri jejaknya dengan kecurigaan sehat, pola-pola ganjil mulai muncul ke permukaan.
Salah satu pola yg mencurigakan adalah bentuknya yg berasrama. Sistem ini, kalau dilihat dalam konteks sejarah Islam, justru bukan berasal dari Timur Tengah. Di Mekkah, Madinah, Damaskus, atau Kairo, pendidikan tradisional berlangsung di masjid, halaqah, atau madrasah yg terbuka. Para murid bebas tinggal di rumah masing-masing atau mengontrak di sekitar pusat belajar. Sistem asrama yg ketat, di mana para murid tinggal di bawah supervisi langsung seorang guru, jauh lebih dekat dengan tradisi boarding school Eropa yg berkembang sejak zaman pertengahandi Inggris, Prancis, & Belanda.
Modelboarding schoolEropa bukan sekadar tempat belajar. Ia adalah alat pembentukan tabiat & kontrol sosial. Di Eropa, ia berada di bawah pengaruh gereja, membentuk generasi yg patuh pada hierarki religius & politik. Saat model ini dibawa ke wilayah koloni, fungsi itu tetap dipertahankan: mendidik elite lokal supaya loyal pada kekuasaan kolonial, menanamkan nilai-nilai Kristen Barat, & membentuk mentalitas tunduk kepada struktur kekuasaan yg ada. Proses ini halus, nyaris tak terasa, tetapi dampaknya menembus generasi demi generasi.
Jika demikian, apakah mungkin pesantren adalah adaptasi lokal dari pola ini? Apakah sistem berasrama, kepatuhan total pada kiai, & pola supervisi ketat yg kita kenal sekarang sebenarnya merupakan warisan dari model pendidikan kolonial yg disesuaikan dengan cita rasa Islam Nusantara? Pertanyaan ini semakin relevan ketika kita melihat disparitas mencolok antara pesantren di Jawa & lembaga pendidikan Islam di daerah lain, seperti Aceh, yg lebih terbuka & tidak memaksa murid tinggal di asrama.
Ada satu aspek menarik yg jarang dibicarakan: istilah santri. Secara etimologis, ia sering dihubungkan dengan mengatakan Sanskerta yg berarti orang berilmu. Namun ada pula tafsir simbolik yg lebih provokatifmengaitkannya dengan threesuns atau tiga matahari, representasi Trinitas dalam Kekristenan. Dalam ikonografi gereja, tiga mentari melambangkan Bapa, Anak, & Roh Kudus. Jika ini benar, maka istilah santri mungkin tidak lahir murni dari kosakata Islam, melainkan merupakan hasil pertemuan, atau bahkan benturan, antara simbol-simbol Islam & Kristen dalam konteks kolonial.
Kita tahu bahwa pada masa Hindia Belanda, kristenisasi tidak sering dilakukan secara terang-terangan. Ia kerap beroperasi lewat strategi kultural, meminjam bahasa, simbol, bahkan metode pengajaran yg sudah diketahui masyarakat. Pendidikan jadi jalur utama infiltrasi ini. Sebuah istilah yg kita anggap Islam dapat saja mengandung muatan simbolis yg diambil dari tradisi lain, lalu ditanamkan dalam pencerahan kolektif tanpa pernah disadari.
Bukti-bukti historis menunjukkan bahwa hubungan pesantren dengan kekuasaan kolonial tidak sesederhana yg kita bayangkan. Banyak pesantren pada masa kolonial yg bersikap apolitis, memilih beradaptasi daripada melawan. Tidak sedikit kiai akbar yg menerima dukungan, baik berupa izin pendirian, pemberian tanah, maupun bantuan logistik dari pemerintah kolonial. Dalam beberapa kasus, pesantren jadi tempat pembinaan calon pejabat pribumi yg kemudian diintegrasikan ke dalam birokrasi kolonial.
Contoh yg paling memancing pertanyaan adalah kasusKiai Sadrach.Iaseorang pemimpin komunitas Kristen pribumi yg mengadopsi gaya keislaman: mengenakan sorban, berkhotbah dari mimbar, & menampung murid-muridnya dalam sistem berasrama. Ajarannya murni Kristen, tetapi kemasan metodenya identik dengan pesantren. Fakta ini menunjukkan bahwa batas antara pesantren, misi Kristen, & strategi kolonial pernah begitu tipis sehingga nyaris tak terbedakan.
Jika kita tarik benang merahnya, sistem berasrama dalam pesantren dapat saja merupakan adaptasi dari pola pendidikan yg sudah lama dipakai oleh misionaris & administratur kolonial. Di Eropa, model ini memproduksi generasi yg patuh pada otoritas gereja & negara. Di koloni, ia memproduksi elite lokal yg loyal pada tatanan kolonial. Pola patronklien antara guru & murid di pesantrendi mana kiai jadi figur pusat & otoritas mutlakselaras dengan kebutuhan kolonial untuk menciptakan hierarki sosial yg stabil & mudah dikendalikan.
Dampak psikologisnya juga signifikan. Santri dibentuk bukan cuma untuk memahami teks agama, tetapi juga untuk hidup dalam kerangka disiplin yg ketat, menerima otoritas tanpa perlawanan, & mematuhi tata tertib tanpa mempertanyakan logikanya. Disiplin ini, dalam perspektif kekuasaan, sangat berguna untuk memelihara keteraturan sosial yg menguntungkan penguasa.
Dari sini muncul hipotesis yg tidak menyenangkan bagi banyak orang: pesantren yg kita kenal hari ini mungkin tidak sepenuhnya lahir dari tradisi Islam murni, melainkan merupakan hasil hibridisasi antara warisan Islam, adaptasi lokal, & rekayasa sosial kolonial. Dengan mengatakan lain, pesantren dapat saja merupakan instrumen pengendalian sosial yg dibungkus dalam legitimasi religius.
Hipotesis ini tentu saja menuntut kajian lanjutan. Tetapi keberanian untuk mengajukannya adalah langkah awal dalam membongkar lapisan-lapisan sejarah yg selama ini dianggap tak tersentuh. Sejarah tidak pernah tunggal; ia sering merupakan hasil dari perebutan narasi, tempat berbagai kepentingan saling bertarung untuk menentukan versi mana yg akan diabadikan sebagai kebenaran.
Membongkar sejarah pesantren bukan berarti menafikan peran positifnya hari ini. Banyak pesantren sudah jadi pusat pemberdayaan masyarakat, melahirkan ulama, akademisi, bahkan aktivis sosial. Namun, kalau akar sejarahnya memang bersinggungan dengan kolonialisme & kristenisasi, kita perlu menyadari bahwa sebuah lembaga dapat saja membawa warisan struktur kekuasaan yg tidak lagi kita sadari, tetapi tetap bekerja secara laten.
Tugas generasi sekarang bukanlah memuja atau menghujat tanpa dasar, melainkan mengerjakan rekonstruksi. Kita perlu menata ulang narasi pendidikan Islam di Nusantara supaya benar-benar membebaskan, bukan sekadar meneruskan pola yg dulu dirancang untuk mengendalikan. Pendidikan Islam tidak boleh berhenti pada pengajaran doktrin & hafalan teks, tetapi harus mengajarkan keberanian untuk bertanya, membantah, & berpikir mandiri.
Mungkin, inilah paradoks terbesar pesantren. Ia dibanggakan sebagai benteng pertahanan Islam, namun bentuknya dapat saja mewarisiblue printlembaga pendidikan kolonial. Ia dibanggakan sebagai pusat perlawanan, tetapi strukturnya sangat cocok untuk penanaman loyalitas & kepatuhan mutlak. Dan mungkin, justru di sinilah letak tantangannya: bagaimana mengubah sebuah institusi yg secara historis pernah jadi instrumen kontrol jadi ruang yg benar-benar membebaskan pikiran.
Sejarah, kalau dibaca dengan mata terbuka, jarang memberikan kenyamanan. Ia mengungkap hal-hal yg harap kita lupakan. Ia memaksa kita mempertanyakan fondasi yg kita anggap kokoh. Dalam kasus pesantren, mempertanyakan akar sejarahnya bukanlah tindakan meruntuhkan, melainkan membuka kemungkinan untuk membangun kembalidengan pencerahan penuh bahwa pendidikan adalah medan perjuangan, & setiap bentuknya sering membawa jejak kekuasaan di dalamnya.



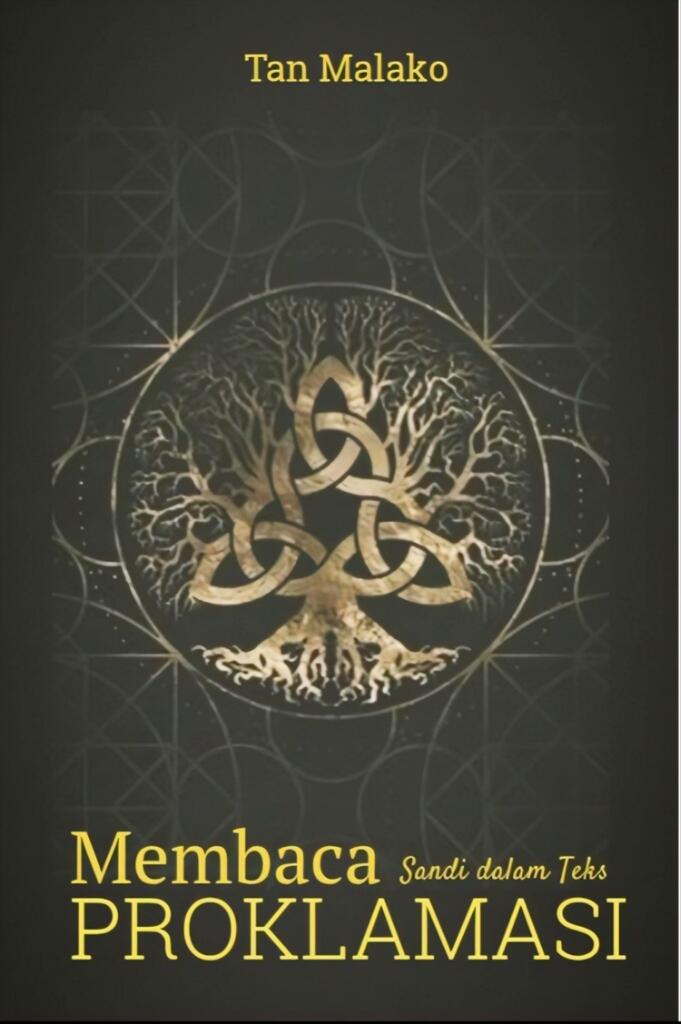



![[HOT ISSUE] Pajak Tanah Naik 4001000%, Warga Menjerit!](https://wgnewss.com/wp-content/themes/newscrunch/assets/images/no-preview.jpg)