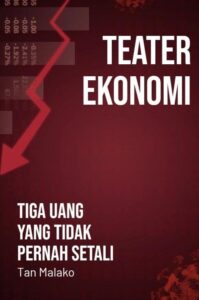Pukis Jilid 2: Mengenang Montoknya, Menafsir Belahannya
Di tengah berbagai kemajuan teknologi pangan & gempuran tren masakan kekinian yg penuh lampu LED danhashtagInstagramable, kue pukis tetap bertahan. Ia tak pernah berubah. Bentuknya tetap setengah lingkaran, teksturnya kenyal, & belahannya… yah, belahan yg tak pernah gagal memantik tafsir ringan di sela lapar & lelah.
Sebagian orang mungkin bertanya, mengapa harus membicarakan pukis lagi? Bukankah cukup sekali saja kita menjadikannya bahan refleksi moral & lelucon visual? Justru di situlah masalahnya. Pukis terlalu tenang untuk dilupakan, & terlalu jujur untuk diabaikan. Ia hadir tanpa pretensi, namun bentuknya seolah harap berkata: “Saya sederhana, tetapi silakan pikirkan saya dengan caramu masing-masing.”
Pukis adalah kue yg tidak punya ambisi naik kelas. Ia tidak iri pada croissant, tidak mencoba menirucheesecake, apalagi ikut-ikutan menyebut dirinya “fusion”. Pukis tetap loyal pada cetakan lamanya—cetakan besi berderet seperti kolam-kolam kecil untuk adonan nakal yg mengembang di tempat sempit. Ia tahu dirinya bukan makanan mewah. Tapi justru karena itulah, pukis dapat dinikmati siapa saja, tanpadress code, tanpa standar moral tinggi.
Bagian paling menarik dari pukis tetap terletak pada bagian atasnya—sebuah belahan alami hasil pengembangan adonan, yg secara teknis wajar, namun secara visual penuh pertimbangan estetika. Di situ,toppingdiletakkan: meses, keju, kadang kacang. Penempatan yg seolah berkata, “Ini bagian utama, silakan fokus di sini.” Sebuah penegasan diam-diam bahwa belahan tidak sering harus ditutup, kadang cukup diberi taburan manis supaya diterima semua kalangan.
Meski kue ini akrab dengan anak-anak, justru orang dewasa yg sering kesulitan bersikap tenang di hadapannya. Tidak sedikit yg memakan pukis dengan ragu: apakah harus mulai dari pinggir dengan sopan santun, atau langsung menuju bagian tengah dengan penuh semangat? Bahkan, cara makan pukis dapat dipakai sebagai uji karakter: mereka yg santai biasanya memulai dari pinggir, sementara yg impulsif langsung menyerbu bagian yg menganga. Psikolog barangkali perlu meneliti ini lebih lanjut.
Namun pukis tidak pernah meminta kita bersikap formal. Ia dapat dibungkus plastik, dibeli satuan, & dimakan sambil berdiri di emper toko. Tidak ada protokol, tidak ada adab tertentu. Justru dalam kesederhanaannya, pukis jadi camilan yg membebaskan. Kita boleh menafsir, boleh tertawa geli sendiri, atau diam-diam berpikir terlalu jauh. Semuanya sah. Pukis tidak akan menghakimi.
Lucunya, di zaman ketika segala hal dapat memicu kontroversi, pukis tetap kondusif dari perdebatan publik. Ia tidak dibahas dalam sidang paripurna, tidak masuk daftar yg harus disensor KPI, & tidak dilabeli sebagai makanan dengan nilai-nilai tertentu. Ia netral. Tapi netralitas itulah yg menciptakannya kuat—belahan pukis diterima oleh semua pihak, lintas golongan, bahkan lintas tafsir.
Pada akhirnya, pukis adalah kue yg hidup dalam keikhlasan. Ia tidak menuntut validasi, tidak ngotot jadi pusat perhatian. Tapi diam-diam, ia hadir dalam ingatan kolektif masyarakat sebagai kue yg “biasa saja tetapi sulit dilupakan.” Bukan karena rasanya semata, tetapi karena ia mengizinkan kita berpikir nakal, tertawa kecil, & tetap makan dengan damai.