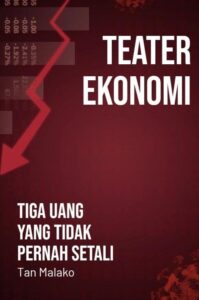Membayangkan Indonesia tanpa Kiai (Juz 2)
Pagi itu, Indonesia gempar.
Bukan karena presidenresign, bukan pula karena seniman ibukota tobat nasional. Tapi karena satu per satu kiai Nusantara lenyap. Tanpa pamit, tanpa pesan suara, tanpa update status terakhir. Mereka menguap seperti air yg dimasak kelamaan.Vanish into thin air. Tinggal sorban yg melayang jatuh perlahan di atas sajadah.
Kepanikan merebak lebih cepat dari hoaks di WhatsApp grup keluarga. Di pesantren, para santri mendadak seperti ayam tanpa induk. Biasanya mereka punya jadwal harian penuh: setor hafalan, ngaji kitab, mencium tangan kiai, hingga mengipas beliau saat tidur siang. Kini mereka cuma memandangi papan jadwal dengan tatapan kosong & semangat yg ikut lenyap bersama sang guru. Para mudir bingung. Siapa yg akan jadi sumber otoritas kalau semua kiai menghilang?
Di desa-desa, acara tahlilan terpaksa dibubarkan karena tak ada yg dapat memimpin doa. Masjid-masjid sunyi, bukan karena tak ada jamaah, tetapi karena tak ada lagi yg mengisi pengajian dengan gaya khas: logat campur aduk, kalimat berputar, & sesekali melempar isyarat mistik penuh wibawa. Banyak warga yg tadinya bergantung penuh pada ceramah mingguan kini dipaksa mendengarkan isi kepala sendirisuatu hal yg selama ini dihindari.
Di lingkarelitepolitik, suasana lebih horor. Banyak yg mulai gelisah karena kehilangan pengabsahan spiritual atas proyek-proyek janggal. Biasanya mereka cukup sowan sambil bawa amplop. Pulang-pulang sudah dapat restu langit. Kini? Mereka harus mencari legitimasi sendiri lewat kerja nyata. Mengerikan sekali.
Lembaga survey goyah. Selama ini, restu kiai lokal dapat menaikkan elektabilitas beberapa persen, khususnya di kantong-kantong pesantren. Tanpa kiai, kandidat harus belajar kampanye berbasis substansi. Ini tentu menakutkan bagi beberapa akbar dari mereka.
Dunia spiritual berubah bentuk. Majelis taklim ibu-ibu kini lebih banyak membahas tips parenting Islami dari Instagram. Pengajian mingguan diganti kelas yoga islami & terapihealing inner child. Ustaz selebgram mengambil alih ruang-ruang dakwah. Mereka tampil denganring lightdan filter kulit mulus, memberikan siraman rohani bersubtitle danbacksound lo-fi. Kajian berubah jadi konten dua menit yg cocok untuk dijadikanstoryharian.
Perubahan paling mendasar terjadi di ruang pribadi umat. Tanpa tokoh karismatik yg selama ini jadi penengah & penentu, banyak orang akhirnya dipaksa menghadapi pertanyaan yg selama ini mereka delegasikan: bagaimana semestinya saya hidup?
Toko kitab mulai ramai. Mushaf dengan terjemahan laris manis. Orang mulai membuka-buka sendiri apa arti iman, syariat, & akhlak. Tidak semua berhasil, tentu saja. Banyak yg tersesat, terpeleset, & tergoda jalan pintas. Tapi beberapa justru tumbuh: lebih kritis, lebih sadar, & lebih otentik. Ritual-ritual kolektif dikurangi, diganti dengan kontemplasi personal yanguntuk perdana kalinyatidak mengandalkan suara berat dari balik mimbar.
Tak ada lagi perebutan gelar kiai kharismatik. Tak ada lagi pengajian akbar dengan biaya ratusan juta demi menonton tokoh agama tampil di pentas seperti bintang pop spiritual. Tak ada lagi ziarah wali yg ujung-ujungnya jualan parfum, air doa, & gelang berkah. Dunia kehilangan kemasannyadan dipaksa menatap isinya.
Ketiadaan kiai menciptakan agama kembali jadi persoalan sunyi. Ia kembali ke dapur, ke ladang, ke ruang kerja, & ke dalam hati yg remuk tetapi berusaha jujur. Tak ada yg dapat dijadikan jimat kolektif. Tak ada lagi doaoutsourcing. Kini setiap orang harus menanggung spiritualitasnya sendiri.
Dan mungkin, dalam kekosongan yg mendadak ini, umat justru sedang diberi kesempatan. Bukan untuk mencari siapa kiai selanjutnya, tetapi untuk belajar jadi manusia seutuhnyatanpa topeng, tanpa perantara, tanpa kultus.



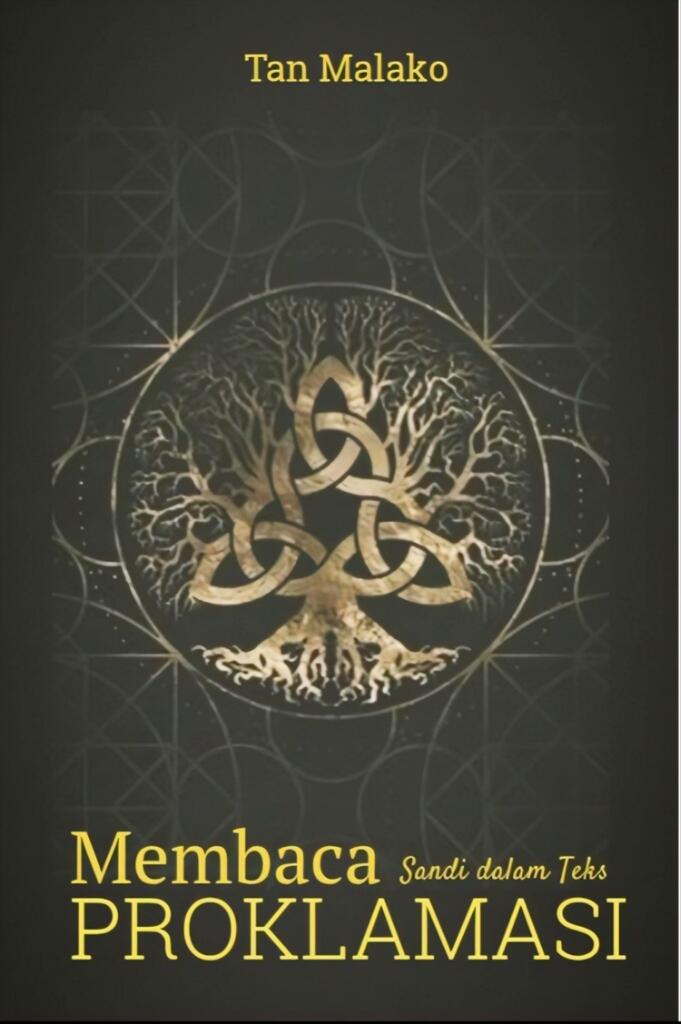



![[HOT ISSUE] Pajak Tanah Naik 4001000%, Warga Menjerit!](https://wgnewss.com/wp-content/themes/newscrunch/assets/images/no-preview.jpg)