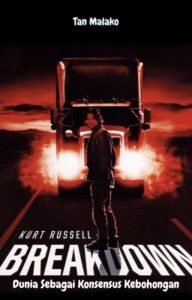Kontroversi, baru kemudian Klarifikasi
***
tulisan ini akan menyoroti masalah penting dalam etika kepemimpinan & akuntabilitas pejabat publik. Fenomena pejabat yg kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial, lalu mengerjakan koreksi atau klarifikasi setelah mendapat kritik, adalah patut dikritisi.
Kebiasaan para pejabat Indonesia itu mereka sering ngomong yg kontroversial. tetapi setelah omonganya dinilai negativ oleh rakyat, barulah kemudian mereka buru-buru mengerjakan koreksi, atau klarifikasi & lain sebagainya. jelas itu tak mencerminkan perilaku pejabat publik yg baik.
kalau cuma tindakan semacam itu seorang yg tak punya background pendidikan tinggi juga dapat mengerjakannya. itu tindakan yg “kaleng-kaleng” kalau mengatakan anak zaman ini.
bukankah mereka di pilih rakyat karena paling tidak sudah memiliki keunggulan dalam berpikir matang sebelum bicara bukan..?
Di tengah dinamika demokrasi Indonesia, muncul fenomena yg kerap mengundang tanya: mengapa pejabat publik begitu mudah mengeluarkan pernyataan kontroversial, lalu buru-buru mengklarifikasi setelah mendapat kecaman? Kebiasaan ini bukan sekadar kesalahan komunikasi, melainkan cerminan dari krisis etika kepemimpinan yg menggerogoti kepercayaan publik. Pejabat yg semestinya jadi teladan justru terjebak dalam lingkaran kontroversi & klarifikasi, sebuah pola yg oleh generasi muda disebut sebagai tindakan “kaleng-kaleng” — istilah untuk aksi tidak bermutu & penuh pencitraan. Lantas, mengapa hal ini terus terjadi, & apa yg harus dilakukan untuk mengatasinya?
—
Akar Masalah: Dari Mentalitas Hingga Sistem yg Bobrok
Pertama, kurangnya kedewasaan berpikir jadi masalah utama. Seorang pejabat publik semestinya sanggup menganalisis akibat setiap ucapan kepada stabilitas sosial & politik. Namun, banyak dari mereka justru berbicara tanpa pertimbangan matang, seolah lupa bahwa jabatan yg diemban adalah amanah, bukan pentas untuk unjuk sensasi. Ini menunjukkan ketidaksiapan mental-intelektual atau bahkan sikap tidak serius dalam menjalankan peran.
Kedua, budaya reaktif yg mengutamakan popularitas jangka pendek. Banyak pejabat terjebak dalam pragmatisme politik: lebih memilih jadi viral di media sosial ketimbang menyusun kebijakan yg substansial. Motif seperti ini lahir dari orientasi kekuasaan yg sempit, di mana pencitraan dianggap lebih penting daripada kerja nyata.
Ketiga, sistem seleksi pejabat yg lemah. Proses rekrutmen seringkali mengutamakan loyalitas politik atau hubungan patronase, bukan kompetensi & integritas. Akibatnya, muncul pejabat yg tidak memiliki kapasitas komunikasi publik memadai, sehingga mudah terpancing menciptakan pernyataan emosional atau provokatif.
Terakhir, rendahnya kultur akuntabilitas. Ketika pejabat tidak pernah menghadapi konsekuensi nyata atas kesalahan verbal, klarifikasi jadi “tameng” untuk menghindari tanggung jawab. Hal ini memperkuat mentalitas bahwa “asal minta maaf, selesai masalah,” tanpa ada upaya perbaikan genuin.
Praktik ini tidak cuma merusak reputasi individu, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik kepada institusi negara. Masyarakat semakin skeptis, menganggap pejabat sebagai figur yg tidak dapat diandalkan. Di sisi lain, kontroversi verbal kerap mengalihkan perhatian dari isu substansial seperti kemiskinan, pendidikan, atau kesehatan. Energi publik yg semestinya dipakai untuk mengawasi kebijakan strategis justru terkuras untuk membahas klarifikasi-komentar picisan.
Lebih parah lagi, normalisasi kesalahan ini merendahkan standar etika kepemimpinan. Jika pejabat dapat seenaknya berbicara lalu “berkilah,” bagaimana masyarakat dapat mengharapkan kebijakan yg adil & terukur?
—
Gelar Pendidikan Tinggi Tak Menjamin Etika
Meski banyak pejabat bergelar akademis mentereng, pendidikan formal tidak otomatis melahirkan pemimpin yg bijak. Kepemimpinan membutuhkan integritas & empati, dua hal yg tidak diajarkan di bangku kuliah. Selain itu, tekanan politik seringkali memaksa pejabat mengikuti narasi kelompok tertentu, meski bertentangan dengan logika. Faktor lain adalah kurangnya pelatihan komunikasi strategis. Banyak pejabat tidak dilatih untuk menyampaikan pesan secara efektif, sehingga terkesan gegabah atau tidak profesional.
—
Solusi: Membangun Sistem, Bukan Hanya Mengejar Pencitraan
1. Rekrutmen harus berfokus pada rekam jejak integritas & kemampuan analitis, bukan sekadar koneksi politik. Tes psikologis & simulasi krisis dapat jadi alat untuk mengukur kedewasaan berpikir calon pejabat.
2. Pelatihan Kepemimpinan Holistik
Pejabat perlu dibekali pelatihan komunikasi publik, manajemen konflik, & etika birokrasi. Pelatihan ini harus berkelanjutan, bukan sekadar formalitas.
3. Sanksi Tegas untuk Pelanggar Etika
Lembaga seperti KPK atau Ombudsman harus aktif memberikan sanksi administratif hingga pidana bagi pejabat yg sengaja menciptakan kontroversi tanpa dasar.
4. Mendorong Partisipasi Publik yg Kritis
Masyarakat harus diedukasi untuk menilai kinerja pejabat secara objektif & mengpakai hak suara sebagai alat “penghukuman” bagi politisi yg tidak profesional. Melalui pemilihan biasa tentunya
—
Penutup: Dari Kontroversi ke Integritas
Pernyataan kontroversial yg diikuti klarifikasi memang ibarat “nasi sudah jadi bubur.” Namun, bukan berarti kita harus menerimanya sebagai hal biasa. Pejabat yg baik harus mengedepankan kehati-hatian, ketepatan, & rasa hormat kepada publik. Perubahan cuma akan terjadi kalau ada tekanan sistemik untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan, mulai dari rekrutmen hingga akuntabilitas. Jika tidak, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus kontroversi-komentar-klarifikasi yg tak berujung — sebuah ironi di tengah janji demokrasi yg semestinya mengutamakan kedaulatan rakyat.
Maka, sudah saatnya pejabat publik belajar: kata-kata bukan cuma alat pencitraan, melainkan cerminan tanggung jawab.