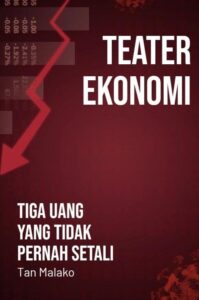Kapitayan & Tai Kopi: Tafsir Bebas dari Lorong Belakang
Di zaman sekarang, spiritualitas sudah seperti warung kopi kekinian: semua orang dapat bikin sendiri, racik sendiri, jual sendiri, lalu bilang, “Ini resep nenek moyang.”
Apa pun dapat diklaim sebagai tradisi asli Nusantara.Mau kopi dengan krimer kelapa sawit? Tinggal bilang: “Ini warisan Majapahit.”
Mau meditasi sambil scroll TikTok? Bisa dikemas dengan embel-embel: “Ini olah batin leluhur.”
Salah satu yg belakangan ramai adalah soal Kapitayan.Kata beberapa orang, Kapitayan adalah agama asli Nusantara sebelum Hindu-Buddha masuk. Tuhan yg disembah namanya Sang Hyang Taya, yaitu Tuhan yang… kosong. Tak dapat dibayangkan, tak dapat didefinisikan, bahkan tak dapat disebutkan. Pokoknya, Tuhan versiblank page.
Agak jenaka sebenarnya. Karena kalau Tuhan sudah dideklarasikan sebagai “kosong”, berarti siapa pun bebas isi sesuai selera. Mau diisi dengan sayang kasih? Boleh. Mau diisi dengan marketing MLM? Monggo. Mau diisi dengan endapan pikiran pas habis ngopi? Sah-sah saja.
Di warung kopi, Kapitayan sering jadi bahan guyonan. Orang-orang menyebutnya coffee-tay-an.
Coba ucapkan cepat-cepat:
“Kapitayan…coffee-tay-an… Kopitaian. “
Lama-lama lidah terpleset sendiri.
Tentu ini bukan sekadar plesetan iseng. Ini sindiran tentang betapa gampangnya hari ini orang bikin spiritualitas baru, lalu bilang: “Ini ajaran asli Nusantara.”
Padahal, kadang rasanya seperti kopisachetyang diaduk asal jadi: pahitnya nanggung, manisnya kebanyakan, tetapi dibungkus dengan cerita-cerita tentang warisan budaya. Pokoknya, spiritualitas rasa kopi. Seduh sendiri, tafsir sendiri.
Bahkan, ada yg bilang, kopi yg diaduk sambil merenung sore-sore itulah yg menginspirasi nama kapitayan. Bukan dari prasasti, bukan dari naskah kuno, tetapi dari dialog di pinggir warung: “Bro, coba-coba bikin agama yuk, namanya Kapitayan, biar lokal & mistis.”
Kalau bicara soal kopi, jangan lupa ada yg tertinggal di dasar gelas: ampas semesta.
Ampas ini dapat diibaratkan sisa-sisa lamunan, tafsir dadakan, atau kadang sisa aktivitas yg tak mau diakui di depan publik.
Begitu juga dengan spiritualitas yg katanya “asli dari leluhur.” Kadang bukan benar-benar warisan purba, tetapi sisa-sisa ide yg diendapkan semalam di kedai kopi.
Besok paginya langsung viral di media sosial, lengkap dengan caption:
“Temukan kembali jati diri Nusantara.”
Padahal ya isinya… ya itu tadi: endapan metafisik dari gelas kopi semalam.
Di lingkungan pesantren, ada istilah mairil.
Katanya sih, secara harfiah, mairil itu dzikir diam-diam, menyebut Tuhan dalam hati.
Tapi, seperti biasa, di masyarakat kita banyak istilah yg mengalami perluasan makna. Mairil kadang diasosiasikan dengan kegiatan main belakang yg dilakukan sembunyi-sembunyi. Bukan cuma soal spiritual, tetapi juga soal selera yg tak sesuai norma umum.
Setelah lulus pesantren, tradisi ini kadang tetap terbawa keluar. Ada yg melanjutkan kebiasaan nyempet, alias curi-curi kesempatan. Kadang nyempet makan, kadang nyempet tidur, kadang nyempet… ya, yg begitu-begitu.
Akhirnya lahir semacam tradisi tafsir dari lorong belakang. Karena tidak dapat mengakses pentas utama, ya tafsirnya dibuat di belakang saja, diam-diam, jauh dari rumah kiai.
Lucunya, fenomena Kapitayan kadang terasa mirip dengan praktik ini. Diam-diam, di luar jalur resmi agama-agama besar, lalu muncul tafsir baru tentang Tuhan yg tak boleh disebut. Karena kalau disebut, nanti ketahuan siapa yg sebenarnya mengarang.
Sekarang ini memang zamannya tafsir bebas. Semua orang dapat bukafranchisespiritualitas sendiri.
Tuhan kosong? Silakan isi sesuai selera pribadi.
Ajaran baru? Ambil dari lorong belakang sejarah, tempelkan label “tradisi asli Nusantara.”
Literatur? Ah, nggak perlu! Cukup bilang: “Ini ilmu batin yg diwariskan secara getaran.”
Getarannya terasa? Ya, mungkin karena efek kopi robusta yg kebanyakan.
Kalau begini terus, kita dapat membayangkan masa depan spiritualitas seperti warung kopi kekinian. Ada menu baru setiap bulan.
Bulan ini “Sang Hyang Taya Latte.”
Bulan depan “Nyempet Macchiato.”
Kalau laris, dapat dibuka cabangfranchisedi setiap sudut kota.
Masalahnya, sejarah itu bukan adonan yg dapat diaduk seenaknya. Tapi hari ini, banyak yg mengaduk-aduk sejarah lalu mengklaim:
“Ini ajaran pra-Hindu, pra-Buddha, pra-Islam, bahkan pra-manusia.”
Ada yg bilang Kapitayan sudah ada sejak zaman batu. Loh, zaman batu kok sudah paham Tuhan kosong? Mereka baru dapat bikin kapak, kok tahu konsep metafisik?
Tapi kalau ditanya buktinya, jawabannya sering begini:
“Ini pengetahuan yg diwariskan lewat bisikan gaib.”
Ya, bisikan itu mungkin datang waktu nyempet tidur di warung kopi sore hari.
Atau waktu ngaduk kopi sambil mikirin endapan metafisik di dasar gelas.
Mari jujur saja: banyak tren spiritual hari ini sebenarnya adalah selingan dari kejenuhan modernitas. Di tengah hidup yg makin cepat, orang butuh ruang pelarian. Kalau agama formal terlalu kaku, maka dibuatlah tafsir bebas yg lebih cair—kadang terlalu cair hingga tak terasa lagi batasnya.
Bukan salah siapa-siapa sebenarnya. Ini cuma bagian dari siklus sosial:Ada yg cari makna hidup.Ada yg jualan makna hidup.Lalu sama-sama duduk di warung kopi, mengaduk ampas semesta.
Agama, spiritualitas, bahkan konsep Tuhan, hari ini seperti kopi di warung kekinian:
Bisa dipesan sesuai selera.Bisa diaduk sendiri.Bisa diminum sambil curi-curi waktu nyempet dari rutinitas.Tapi seperti kopi, sering ada ampas di dasar gelas.
Ampas ini adalah sisa-sisa tafsir dari lorong belakang, endapan sejarah yg diolah-olah, atau lamunan yg tak sempat dituliskan dalam kitab kuning.
Kalau memang harap bikin ajaran baru, ya silakan saja. Negara kita menghormati kebebasan beragama—dan juga kebebasan berimajinasi.
Tapi alangkah baiknya kalau kita jujur pada diri sendiri: Apakah ini benar-benar warisan nenek moyang? Atau cuma hasil nyempet tafsir di warung kopi, sambil menatap ampas semesta yg tak pernah benar-benar hilang?
Karena kalau semua spiritualitas jadifranchise, nanti hidup kita isinya cuma menu:
“Tafsir rasa kopi: seduh sendiri, aduk sendiri, tafsir sendiri.”