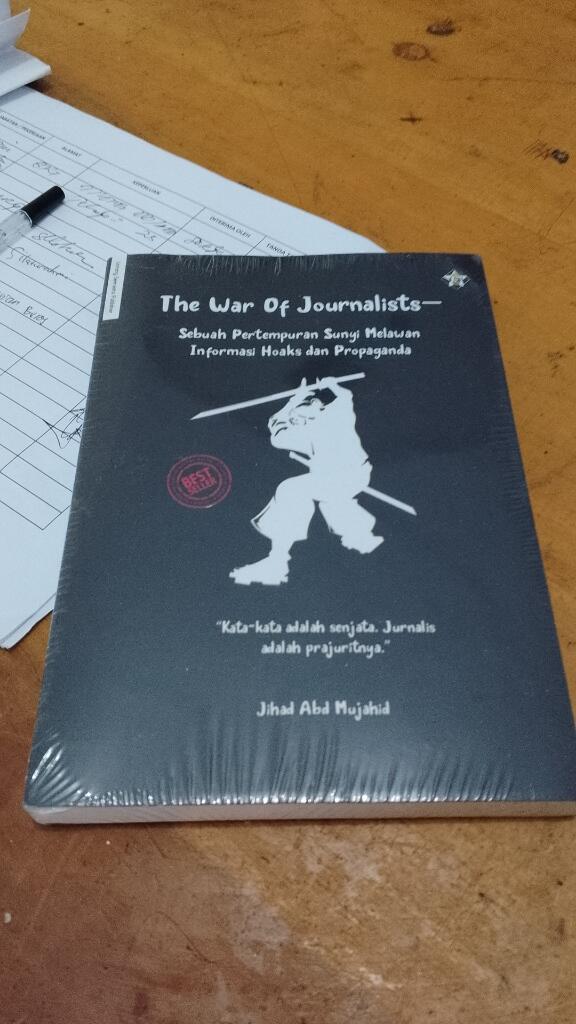Ini Ceritaku Berjuang Untuk Anak Anak Indonesia
22 Mei 2016. Saya berdiri di bawah langit yg mendung di Bandung, Saya mendirikan komunitas bernama SakaBaca, bersama sembilan orang teman yg sama-sama patah tetapi belum mati rasa. Kami tidak punya apa-apa selain tekad & sedikit uang hasil jualan pinggir jalan. Setiap minggu, kami membeli buku. Ya, membeli buku. Padahal kadang makan pun kami tahan.

Saya kuliah di STKIP Fiksi Ganesha Bandung, itu pun karena saya pikir pendidikan dapat menyelamatkan saya dari kemiskinan. Tapi Bandung bukan kota yg ramah bagi orang kecil. Apalagi setelah Wali Kota Ridwan Kamil (2013) menggulirkan penataan kota. Pedagang seperti saya kena sikat. Lapak digusur, penghasilan hilang, kuliah pun harus saya lepas. Ironisnya, di tahun saya berhenti kuliah2015ayah saya meninggal, menyusul ibu saya yg lebih dulu pergi. Saya terjerembab. Tapi tidak tumbang.
Saya mulai mengumpulkan buku. Sedikit demi sedikit. Kadang cuma cukup beli satu buku seminggu. Tapi itu bukan soal jumlah. Itu soal tekad. Saya tidak tahu harus berbuat apa selain membaca & menulis. Saya menulis di blog pribadi saya. Tanggal 8 Juli 2014, saya mengkritik kebijakan dengan tulisan acak acakan , saya menulis artikel berjudul Zona Merah. Tapi siapa yg peduli? Siapa yg mau dengar suara pemuda tanpa gelar, tanpa media, tanpa panggung?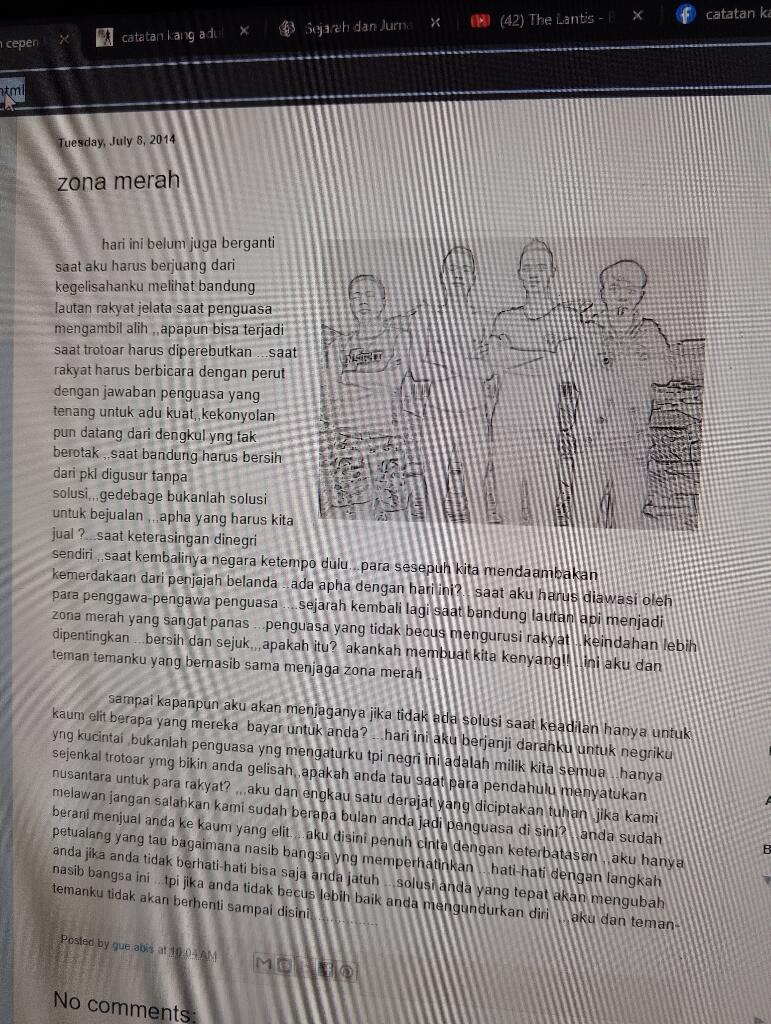
SakaBaca nyaris mati di Bandung. Kami kehadapatn tenaga, kehadapatn uang. Maka saya pulang kampungDesa Tegallega, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut. Di sanalah saya bangun perpustakaan kecil dari sisa-sisa buku yg berhasil saya selamatkan. Tapi desa juga bukan tempat yg ramah bagi orang yg membawa ide aneh. Pendidikan alternatif? Siapa kamu? Uang dari mana? Dukungan dari siapa?
Tapi saya tetap berjalan. Dengan kaki yg luka & dada yg penuh debu. Lalu datang 2 Desember 2016. Saat Jakarta memanas karena demo 212, saya menikah. Saya pikir, mungkin ini babak baru yg lebih damai. Saya pindah ke kampung istri saya, Desa Neglasari, Kecamatan Pakenjeng. Di sana saya bangun komunitas baru: SakaTulis. Saya dirikan rumah. Saya bangun perpustakaan lagi. Tapi hidup tidak pernah seramah itu.
Tiga tahun kemudian, rumah tangga saya kandas. Buku-buku saya, yg dulu saya kumpulkan dengan air mata & peluh, kini tersimpan di gudang. Diam. Sunyi. Seperti saya. Saya berhenti dari semua aktivitas yg dulu saya anggap hidup. Selama tiga tahun, saya seperti mayat hidup. Saya tidak lagi menyebut diri saya “pegiat literasi”, bahkan saya tidak tahu apa itu literasi waktu itu. Yang saya tahu: saya suka belajar, & saya tidak dapat berhenti membeli buku.
Saya mencoba usaha ini-itu. Jualan. Jasa. Apa saja. Tapi selalu, tiap kali ada uang lebih, saya beli buku. Buku adalah satu-satunya hal yg tidak pernah meninggalkan saya.
Lalu tahun 2022, saya diberi kesempatan bekerja di redaksi media lokal Sinar Priangan di Kota Garut. Dua tahun saya belajar keras. Saya pelajari dunia redaksi, liputan, editing. Saya pelajari bagaimana menulis supaya didengar. Dunia media mengajarkan saya satu hal: kalau anda harap suara anda bergema, anda harus tahu caranya menyalakan pengeras suara.
Tapi setelah dua tahun, saya tahu visi saya berbeda. Saya tidak dapat cuma jadi peliput. Saya harap jadi penyambung. Maka saya keluar. Saya bangun media sendiri di bawah PT yg sama: PT Kalam Berita. Saya pindah ke Harian Pedia media lokal yg ada di Garut. Dan dari sana saya membawa kembali mimpi lama saya yg belum selesai: mimpi tahun 2016.
Saya bukan aktivis yg disorot kamera. Saya tidak pernah masuk TV. Tidak pernah viral. Tapi saya berjalan. Saya sering berjalan. Meski terseok. Karena saya percaya, anak-anak dari kampung pun berhak membaca. Berhak pintar. Berhak punya masa depan yg lebih baik.
Saya cuma harap jadi bagian dari perubahan kecil itu. Dari pinggir jalan, dari kampung yg jauh dari pusat kota, dari mimpi yg sempat dikubur tetapi tak pernah benar-benar mati.
Saya pernah kehilangan semuanya. Tapi saya tidak pernah kehilangan hasrat untuk membaca, menulis, & percaya bahwa satu buku dapat menyelamatkan hidup seseorangseperti buku-buku yg pernah menyelamatkan saya.
Hari ini pun, saya masih berjalan. Bukan lagi di Bandung, bukan lagi di kota. Tapi di pelosok Garut Selatan. Tempat di mana sinyal kadang cuma dapat didapat di atas batu akbar atau di bawah pohon jambu. Tempat di mana anak-anak masih terbiasa menggembala kambing sepulang sekolah, atau bahkan tak pernah sekolah sama sekali.

Saya datang ke kampung-kampung. Ke jalan tanah. Ke rumah panggung. Saya cari anak-anak. Saya lihat mata merekamata yg dulu seperti mata saya waktu kecil: penuh tanya, tetapi tak tahu harus tanya ke siapa. Saya peluk mereka lewat buku. Saya ajak mereka menulis, bercerita, bertanya. Karena saya tahu rasanya tumbuh tanpa ada yg mendengar.
Saya tidak harap mereka seperti saya. Tak selesai kuliah. Tak paham sistem. Tersesat di jalan yg saya bangun sendiri, sambil memanggul asa yg entah akan dibawa ke mana.
Hari ini, saya sedang membangun generasi emasbukan dengan dana, bukan dengan program bantuan, bukan dengan lencana. Tapi dengan nurani. Dengan tangan kosong tetapi dada penuh keyakinan.
Kami melawan. Kami melawan kebiasaan diam. Kami melawan takdir bahwa anak kampung harus selamanya jadi penonton. Kami melawan dengan buku, dengan tulisan, dengan suara kecil yg terus kami rawat supaya tak padam. Dan semua itu, tanpa sepeser pun bantuan dari pemerintah.
Tidak ada proposal cair. Tidak ada panggilan audiensi. Tidak ada bapak-bapak berdasi yg datang menepuk bahu lalu hilang. Yang ada cuma kami. Dan nurani kami.
Kami tidak besar. Kami tidak terkenal. Tapi kami nyata.
Saya tahu betul, perjuangan ini mungkin tidak akan mengubah dunia dalam semalam. Tapi kalau suatu hari nanti, satu dari anak-anak di kampung ini jadi penulis, jadi guru, jadi pembela yg jujurmaka saya tahu, semua ini tidak sia-sia.
Saya, seorang mantan pedagang kaki lima, mantan mahasiswa gagal, mantan suami, mantan siapa-siapa. Tapi hari ini saya berdiri sebagai ayah dari ratusan mimpi anak-anak kampung, yg harap dunia tahu bahwa mereka ada, & mereka layak untuk diperjuangkan.
Kami tidak butuh tepuk tangan. Kami cuma butuh didengar.
Dan sementara dunia masih sibuk dengan urusannya sendiri, kami di sini, di pelosok, terus menyalakan pelitameski kecil, meski ditiup angin, tetapi tak pernah padam.
Dan saya juga menulis buku dengan judul the war of journalists sebagai buku perdana & perjuanganku di dunia baca tulis belum berakhir