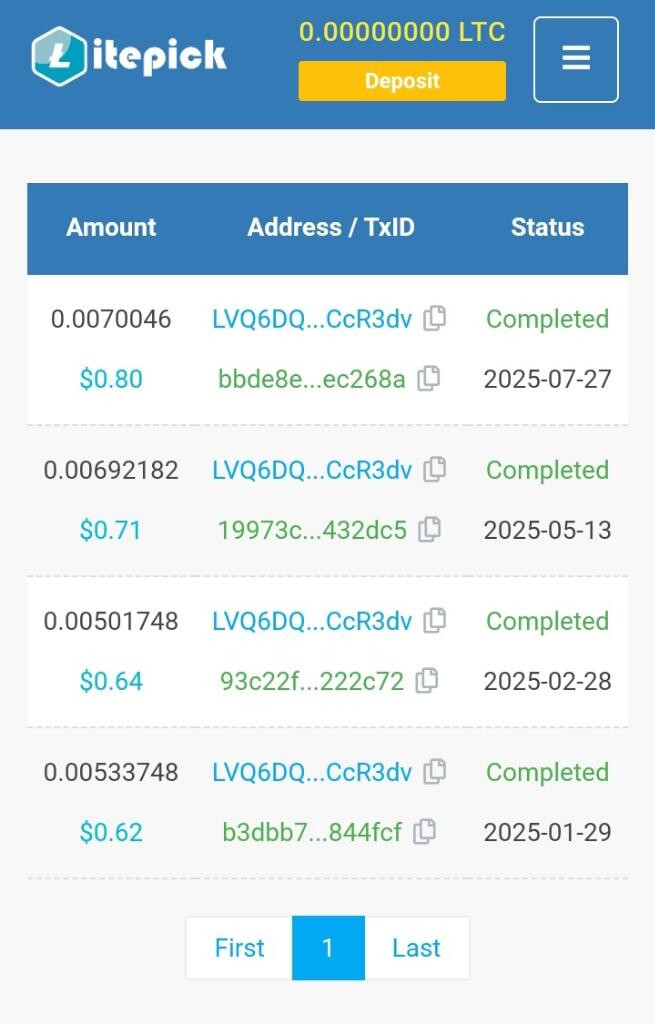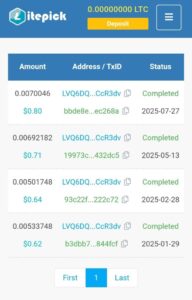Perang, sebuah fenomena yg sudah mewarnai sejarah peradaban manusia, sering kali memicu pertanyaan mendalam tentang rasionalitas & moralitas. Pertanyaan ini jadi semakin mendesak ketika kita menyaksikan akibat tragisnya, khususnya pada kelompok yg paling rentan: anak-anak. Kerugian yg dialami oleh generasi muda ini, baik secara fisik maupun psikologis, tidak cuma menggarisbawahi kegagalan sistemik tetapi juga menempatkan kita pada posisi untuk merenungkan akar konflik itu sendiri.
Pada dasarnya, perang sering kali berakar pada pertentangan kepentingan yg kompleks, mulai dari perebutan sumber daya ekonomi, perselisihan ideologi, hingga ambisi kekuasaan politik. Para aktor di balik layar, yg sering kali berada jauh dari medan tempur, menciptakan keputusan strategis yg dampaknya harus ditanggung oleh masyarakat sipil. Dalam konteks ini, anak-anak jadi korban pasif yg menanggung beban paling berat. Mereka kehilangan masa kecilnya, mengalami trauma yg mendalam, & masa depan mereka jadi tidak pasti.
Fenomena ini mengajak kita untuk mengkaji ulang narasi perang yg sering kali diglorifikasi sebagai tindakan heroik atau keharusan historis. Sebaliknya, perang semestinya dipandang sebagai cerminan dari kegagalan manusia untuk menemukan solusi damai atas disparitas yg ada. Ini adalah kegagalan diplomasi, kegagalan empati, & kegagalan kolektif untuk melindungi mereka yg paling tidak berdaya. Kesadaran ini menuntut kita untuk tidak cuma mengutuk perang itu sendiri, tetapi juga untuk secara aktif mencari & mendukung jalan menuju perdamaian yg berkelanjutan, sebuah jalan yg memprioritaskan dialog, kerja sama, & penghargaan kepada hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak anak-anak untuk hidup dalam damai.