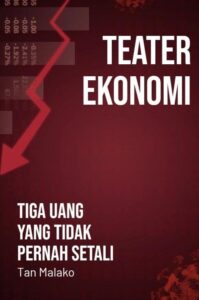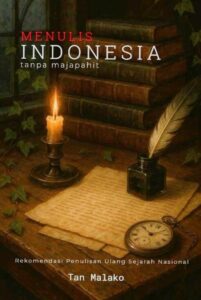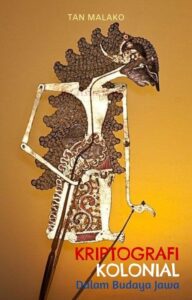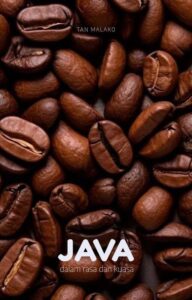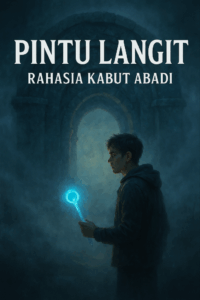Java dalam Rasa & Kuasa
–Benedict R. OG. Anderson
(Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. 1990)
Kopi perdana kali tiba di pulau Jawa sekitar 1696, dibawa oleh VOC dari Mocha, Yaman. Percobaan awal gagal akibat banjir & gempa, tetapi pada 1699 bibit baru ditanam di Priangan & kali ini berhasil. Tak butuh waktu lama sebelum pada 1711, kapal VOC mengangkut kopi Jawa ke Amsterdam untuk dijual di pelelangan. William H. Ukers dalamAll About Coffeemencatat bahwa “kopi Jawa segera jadi barang dagangan yg sangat dicari di pasar Eropa, diketahui karena rasa kuat & aromanya yg khas”. Di balik aroma itu, tentu saja, tersembunyi kerja paksa ribuan petani yg harus menanam kopi bukan karena mereka suka minum kopi, tetapi karena pemerintah kolonial mengatakan begitu.
Namun “Java” bukan cuma kopi. Ia juga sebuah bukti diri etnik yg pada zaman ke-14 jadi inti dari kerajaan Majapahit. Di sinilah muncul istilah yg saya sebut “Jawa Hitam” (kata yg muncul secara ajaib karena acak iseng) -bukan merujuk pada warna kulit atau tipe kopi, tetapi pada campuran sejarah yg disangrai kolonialisme & dibumbui nasionalisme. Majapahit yg kita kenal hari ini bukanlah Majapahit sebagaimana adanya, melainkan Majapahit yg sudah diseduh ulang oleh sejarawan kolonial & politikus modern.
Dalam catatan sejarah kolonial, Majapahit diposisikan sebagai “puncak peradaban” yg kemudian “jatuh” sebelum bangkit kembali dalam wujud negara modern. Aroma narasi ini sedap, tetapi seperti kopi instan, bahan dasarnya sudah diolah sedemikian rupa sehingga rasanya jauh dari aslinya.
Dalam konstruksi kolonial, Jawa dipandang sebagai pusat peradaban di Nusantara, & Majapahit dijadikan simbol kejayaan yg “hilang” & perlu “dipulihkan”. Pandangan ini diadopsi oleh nasionalisme Indonesia awal zaman ke-20. Para tokoh pergerakan, baik sengaja maupun tidak, menyeruput racikan ini. Sama seperti minum kopi Java di kedai Amsterdam, mereka menikmati rasa yg kuat tanpa bertanya siapa yg memetik bijinya. Sejarah jadi seperti minuman: dapat dikemas, diberi merek, dijual, & disesap sesuai selera penguasa.
Jika kita menempatkan kopi Java & bukti diri keJawaan di cangkir yg sama, kita akan melihat kesamaan proses. Biji kopi dipanen, dikeringkan, dipanggang, lalu digiling sebelum diseduh. Sejarah & bukti diri Jawa pun demikian: dipetik dari fragmen masa lalu, dijemur di bawah mentari kolonial, dipanggang dalam wacana politik, digiling dalam kurikulum sekolah, & diseduh dalam pidato-pidato kebangsaan. Hasilnya adalah minuman hangat yg mengandung ampas pahit, tetapi disajikan dengan senyum manis.
Namun seperti halnya kopi, tidak semua orang minum “Java” dalam bentuk hitam pekat. Ada yg menambahkan gula, susu, atau bahkan krim ideologi. Pada era Orde Baru, misalnya, Majapahit dijadikanlattesejarah: banyak busa di permukaan, manis di lidah, tetapi mengandung kafein yg menciptakan kita terjaga cuma untuk melihat satu versi kebenaran. Sebagian sejarahwan mencoba menyajikannya sebagai kopi tubruk–apa adanya, tanpa filter–tetapi pembaca modern sering lebih sukacappuccinonarasi resmi.
Ironisnya, di dunia Barat, “Java” masih lebih sering berarti kopi ketimbang manusia. Bahkan di Amerika Serikat, istilah “a cup ofJava” jadi sinonim untuk secangkir kopi, & bahasa pemrograman yg lahir pada 1995 pun diberi nama Java karena dianggap seperti kopi: menciptakan penggunanya tetap terjaga & produktif. Sementara di Indonesia, mengatakan “Java” lebih sering kita terjemahkan jadi “Jawa”, sebuah bukti diri yg kadang diangkat, kadang ditekan, tergantung siapa yg memegang cangkir.
Kita perlu mengingat bahwa hubungan antara kopi Java & Jawa Hitam sebagai plesetan Majapahit bukan kebetulan belaka. Keduanya adalah hasil perdagangan global, satu melalui kapal dagang & satunya lagi melalui kapal wacana. VOC menjual kopi Jawa ke Eropa; sejarawan kolonial menjual narasi Jawa ke dunia. Di Amsterdam zaman ke-18, seorang pedagang mungkin berkata, “Java ini kuat & pahit, cocok untuk pagi yg dharap.” Di Batavia zaman ke-19, seorang pejabat kolonial mungkin berkata hal serupa tentang penduduk Jawa, cuma mengganti mengatakan “pagi” dengan “politik”.
Humor pahitnya adalah: kita sering meminum kopi tanpa memikirkan petaninya, & kita sering meminum sejarah tanpa memikirkan siapa yg menulisnya. Kita mengagumi aroma, menikmati rasa, tetapi melupakan proses panjang yg melibatkan keringat, paksaan, & manipulasi. Baik kopi maupun sejarah dapat menciptakan kita terjaga, tetapi juga dapat menciptakan kita gelisah, khususnya ketika kita menyadari bahwa yg kita minum adalah hasil seduhan orang lain.
Kini, di kafe-kafe modern Jakarta, secangkir kopi mungkin disajikan oleh barista dengan tato & apron kulit, dihidangkan di meja kayu dengan lampu temaram. Di buku pelajaran, kisah Majapahit disajikan oleh guru dengan pointer laser, dihidangkan di kelas dengan AC menyala. Kedua penyajian ini sama-sama estetik, sama-sama dirancang untuk menciptakan penikmatnya merasa bagian dari sesuatu yg “otentik”. Padahal, otentik di sini hanyalah rasa yg berhasil direkayasa.
Sebagaimana biji kopi yg tidak pernah memilih untuk menjadiespressoataucappuccino, fragmen sejarah tidak pernah memilih untuk jadi narasi nasionalis atau kolonial. Mereka cuma biji: kecil, keras, penuh potensi rasa. Semua tergantung siapa yg memanggangnya, pada suhu berapa, & untuk siapa minuman itu akan disajikan. Dalam hal ini, Belanda mungkin adalah roaster paling berpengaruh dalam sejarah Jawa: mereka memanggang biji kopi untuk pasar dunia, & memanggang bukti diri Jawa untuk pasar politik.
Jadi, ketika kita hari ini menyeruput kopi tubruk tradisional di pagi hari sambil membaca berita politik atau kisah Majapahit di media sosial, kita sebenarnya sedang meneguk dua warisan pahit sekaligus. Satu pahit karena kafein, satu pahit karena kolonialisme. Dan kalau kita tertawa pahit mendengar kisah ini, setidaknya itu tanda kita masih dapat membedakan antara wangi asli biji kopi yg tumbuh dari tanah vulkanik dancoffee fragranceatau aroma kopi sintetis yg disemprotkan ke cangkir
.
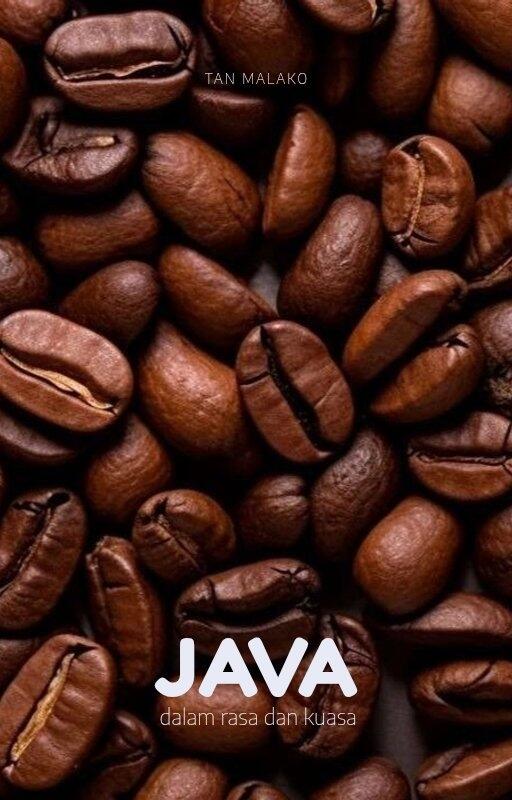
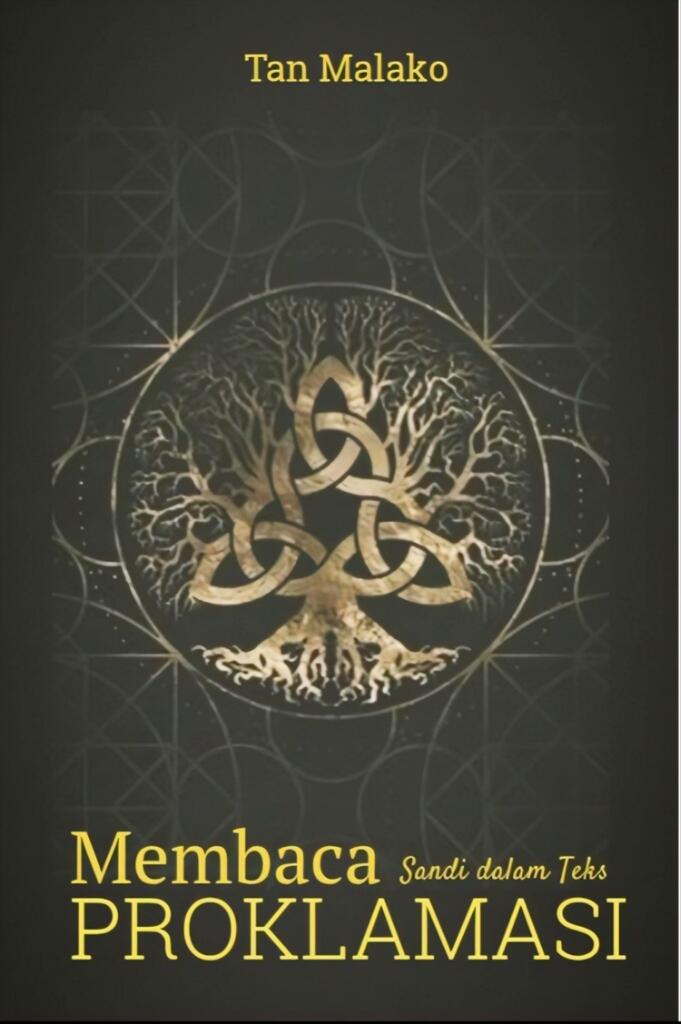

![[HOT ISSUE] Pajak Tanah Naik 4001000%, Warga Menjerit!](https://wgnewss.com/wp-content/themes/newscrunch/assets/images/no-preview.jpg)