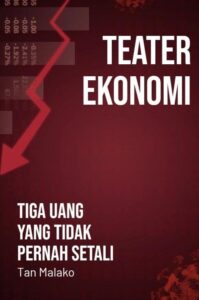Satire Arkeologi dari Trowulan: Kritik Sumber Data Sejarah Majapahit
Masyarakat kita memiliki kebiasaan aneh: mempercayai masa lalu seperti mempercayai ramuan herbal dari iklan televisi—tanpa pernah membaca komposisinya. Ambil contoh Majapahit. Nama ini sering diucapkan dengan nada sakral, seolah setiap bata merah yg muncul di ladang tebu otomatis jadi saksi bisu kejayaan nenek moyang. Padahal, kalau semua bata merah itu benar-benar Majapahit, maka mungkin separuh Jawa Timur adalah candi raksasa yg runtuh karena kelelahan.
Di laboratorium arkeologi, Majapahit tidak dapat dibangkitkan cuma dengan retorika. Ia harus dihidupkan lewat tes karbon, termoluminesensi, stratigrafi, & segala metode ilmiah yg sering dihindari para sejarahwan karena terlalu mengganggu plot nasionalisme.
Candi yg kita klaim dari zaman ke-14 harus diuji komposisi batanya. Kalau ternyata kandungan mineralnya menunjukkan teknik pembakaran modern, maka yg kita hadapi bukan peninggalan Majapahit, melainkan hasil kreativitas tukang batu desa pada tahun 1970 yg mungkin pernah ikut proyek perumahan di Trowulan.
Lalu ada prasasti. Ah, prasasti! Batu dengan ukiran aksara Kawi ini sering dijadikan bukti mutlak. Namun, paleografi tanpa penanggalan material ibarat menikahi seseorang cuma berdasarkan foto masa SMP—kita tidak tahu kondisinya sekarang, apalagi apakah fotonya asli. Ukiran dapat dibuat ulang oleh tukang pahat modern dengan ketelitian yg mengagumkan. Karena itu, batu prasasti harus diuji umur materialnya. Jika hasilnya menunjukkan “lahir” pada 1850, maka jelas ia hanyalah imitasi kolonial yg mungkin dibuat untuk memuaskan rasa lapar Belanda kepada eksotisme Jawa.
Masalah berikutnya adalah konteks situs. Artefak yg benar-benar sezaman akan ditemukanin situ, tertanam di lapisan tanah yg konsisten dengan kronologi lokal. Tetapi banyak “peninggalan Majapahit” muncul tanpa alamat asal, seperti anak yg tiba-tiba mengaku keluarga Anda cuma karena membawa foto lama. Prasasti yg ditemukan di halaman belakang rumah seorang kolektor tanpa catatan penggalian resmi sama meragukannya dengan surat wasiat yg diketik kemarin sore.
Para sejarahwan sering mengeluh bahwa metode ilmiah ini “membunuh kebanggaan bangsa”. Mereka benar dalam satu hal: metode ini memang membunuh kebohongan. Sains tidak peduli apakah hasilnya menciptakan kita bangga atau malu. Jika radiokarbon menunjukkan bahwa sisa arang di dalam candi berasal dari zaman ke-17, maka seluruh pidato tentang “pusaka Majapahit” harus diganti dengan “pusaka Mataram” atau bahkan “pusaka pembakaran dapur umum”.
Namun, permainan satir paling indah muncul ketika kita membandingkan bukti arkeologi dengan sumber asing sezaman. Catatan Tiongkok zaman ke-14, misalnya, dapat menyebut adanya negeri perdagangan di Jawa. Tetapi kalau artefak yg kita temukan sama sekali tidak menunjukkan jaringan perdagangan internasional, maka mungkin yg dimaksud dalam catatan Tiongkok adalah pelabuhan kecil yg di kemudian hari dipromosikan jadi kerajaansuperpoweroleh penulis naskah istana. Ini seperti menemukan kuitansi warung kopi lalu menafsirkannya sebagai bukti bahwa pemilik warung adalah pengendali ekonomi dunia.
Laboratorium juga dapat membongkar tipu daya penuaan buatan. Permukaan batu yg digosok asam atau dibakar ringan supaya terlihat tua akan meninggalkan pola korosi yg tidak alami. Di bawah mikroskop elektron, semua kebohongan itu tampak jelas. Batu tua palsu akan mempermalukan pengagumnya, sama seperti wig murahan mempermalukan pemakainya di tengah angin kencang.
Sayangnya, beberapa akbar narasi Majapahit yg beredar di buku pelajaran tidak pernah melewati tahap verifikasi ilmiah yg ketat. Banyak yg cuma mengulang cerita Nagarakretagama atau Pararaton, yg ditulis dari sudut pandang politik internal istana. Mengandalkan sumber tunggal ini untuk menggambarkan seluruh Nusantara zaman ke-14 sama naifnya dengan mengandalkan brosur hotel untuk memahami sejarah kota tempat hotel itu berdiri.
Dengan metode yg benar, Majapahit dapat menyusut drastis ukurannya. Mungkin ia cuma kerajaan regional dengan beberapa pusat perdagangan, bukan imperium yg membentang “dari Sabang hingga Merauke” seperti yg sering dikhotbahkan. Tetapi inilah risiko penelitian: Anda harus siap menerima kenyataan bahwa kebesaran nenek moyang Anda mungkin cuma sebesar kecamatan.
Ironisnya, kalau kita benar-benar jujur & cuma memakai bukti yg lolos uji otentisitas serta orisinalitas, maka beberapa “warisan Majapahit” yg kita sayangi dapat jadi pindah label jadi “warisan kolonial tentang Majapahit”.
Artinya, apa yg kita yakini sebagai fakta sejarah adalah hasil rekayasa zaman ke-19 yg dirancang untuk memudahkan Belanda menguasai Jawa melalui narasi kejayaan masa lampau. Dan ketika kita melanjutkan narasi itu tanpa kritik, kita sesungguhnya sedang bekerja sebagai humas warisan kolonial, gratis.
Kesimpulannya, menghidupkan Majapahit memerlukan kerja ilmiah yg melelahkan, sering kali menyakitkan bagi para pensayang candi, & sama sekali tidak cocok untuk orasi politik.
Namun, kalau tujuan kita adalah kebenaran, bukan sekadar kebanggaan, maka kita harus rela menyalakan lampu mikroskop & mematikan lampu sorot panggung.
Karena cuma di laboratorium, Majapahit dapat dibuktikan hidup; & cuma di laboratorium pula ia dapat dimakamkan secara terhormat—tanpa pidato panjang, tanpa sumpah Gajah Mada, & tanpa bata merah palsu yg dijual di pinggir jalan.