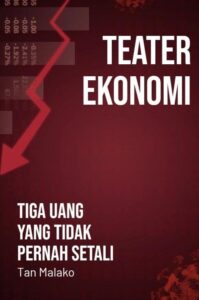Komedi 17 Agustus: Republik dalam Irama Pinggul
Fenomena ini tentu tidak lahir dari ruang kosong. Ia adalah hasil evolusi panjang dalam sejarah tubuh bangsa. Di masa awal kemerdekaan, upacara 17 Agustus ditampilkan sebagai ritual penuh wibawa. Soekarno memosisikan tubuh negara sebagai tubuh revolusioner: tegang, gagah, penuh tenaga historis. Tak ada ruang untuk goyangan yg dapat dianggap sepele. Kemerdekaan adalah sakralitas, bukan pesta. Tubuh para pemimpin harus jadi patung hidup yg menyalurkan aura kekuasaan. Joget cuma mungkin terjadi di kampung halaman setelah upacara usai, diiringi gamelan atau dangdut, bukan di halaman istana.
Kemudian datang Orde Baru, yg mengeras seperti beton. Soeharto memaku upacara jadi barisan batu. Tidak ada irama selain langkah kaki punggawa & suara komando. Tubuh pejabat dilatih untuk menahan diri dari segala macam spontanitas. Dalam ruang itu, joget bukan sekadar tidak pantas, ia adalah kejahatan simbolik. Sebuah gerakan pinggul yg keliru dapat dibaca sebagai tanda subversif. Maka tubuh negara benar-benar membeku. Joget cuma boleh bernafas di gang sempit, dalam lomba tarik tambang & panjat pinang, jauh dari mata penguasa.
Reformasi membawa angin baru, tetapi angin itu masih berhembus pelan. SBY menghadirkan nuansa musik orkestra, pembacaan puisi, & simbol budaya, namun tetap menjaga keseriusan. Tubuh negara mulai melunak, tetapi tidak pernah benar-benar menari. Upacara tetap terasa berat, cuma saja kini dihiasi selapis kesan romantis. Demokrasi memberi ruang untuk bicara, namun tubuh pejabat masih belum diperbolehkan hanyut dalam irama rakyat.
Jokowi mengubah semuanya. Ia membuka pintu istana bagi musik dangdut, busana adat, hingga komedi ringan. Upacara yg dulu kaku berubah jadi semacam festival televisi. Setelah bendera naik, musik populer berdentum, penyanyi tampil, & kamera mencari wajah-wajah pejabat yg tergoda untuk ikut bergoyang. Tangan mulai melambai, kepala mengangguk, pinggulmeski kakuikut berusaha mengikuti alur. Awalnya tampak kikuk, tetapi kemudian jadi kebiasaan. Joget masuk ke dalam protokol tak tertulis: kalau kau tidak ikut bergerak, kau akan tampak asing, bahkan mungkin dianggap tidak selaras dengan semangat zaman.
Pada titik inilah, joget beralih status dari hiburan rakyat jadi bahasa resmi negara. Tubuh pejabat yg dahulu disakralkan kini dipertontonkan sebagai tubuh yg dapat dilenturkan. Tetapi lentur di sini tidak lahir dari kebebasan, melainkan dari tuntutan citra. Negara harus terlihat dekat dengan rakyat, & kedekatan itu dipertunjukkan bukan dengan kebijakan yg menyejahterakan, melainkan dengan gerakan pinggul di hadapan kamera. Politik tubuh bergeser: yg penting bukan apa yg dikerjakan tangan negara, melainkan bagaimana tangan itu melambai di panggung.
Fenomena ini kembali dipentaskan pada HUT RI ke-80 kemarin (17 Agustus 2026), Presiden Prabowo yg selama ini diketahui keras, ikut bergoyang mengikuti lagu populer. Televisi menayangkan momen itu berulang-ulang: seorang jenderal yg dahulu berwajah garang kini tersenyum, melambai, bahkan sedikit menggerakkan pinggul. Para pejabat lain pun ikut, seolah tidak ada opsi selain mengikuti arus. Dari layar kaca, terlihat seperti pesta bersama. Namun di balik itu, ada nuansa keterpaksaan. Tubuh-tubuh itu bergerak seperti boneka tali, lebih karena takut terlihat kaku daripada benar-benar terhanyut dalam irama.
Joget di istana adalah komedi yg serius. Ia jenaka bagi penonton, tetapi serius bagi politik. Ia berfungsi sebagai tirai tipis yg menutupi kenyataan pahit. Rakyat menonton pejabat menari, & sejenak lupa pada harga pangan yg melonjak, utang negara yg menumpuk, atau nilai tukar rupiah yg melemah lebih dari empat juta kali lipat sejak upacara kemerdekaan perdana kali diselenggarakan. Joget jadi narkotika visual: murah, menyenangkan, & efektif mengalihkan perhatian. Nasionalisme yg dulu lahir dari pidato panjang kini dikemas dalam video singkat berdurasi 30 detik yg viral di media sosial.
Namun justru di sinilah letak kekonyolan sekaligus kepahitan bangsa ini. Betapa mudahnya tubuh negara diubah dari patung sakral jadi badut festival. Betapa cepatnya pergeseran dari sakralitas ke kelucuan. Sejarah bangsa, yg dulu ditulis dengan darah & air mata, kini dikaligrafikan dengan keringat di ketiak baju batik serta tawa penonton kepada pejabat yg salah langkah. Jika dulu rakyat dipaksa hormat melalui kekerasan, kini rakyat diarahkan tertawa melalui hiburan. Kedua-duanya adalah bentuk pengendalian, cuma saja dengan rasa yg berbeda.
Apakah ini kemajuan atau kemunduran? Mungkin keduanya sekaligus. Di satu sisi, ada kelegaan karena tubuh negara tidak lagi terlalu kaku. Di sisi lain, ada kekecewaan karena kelonggaran itu tidak benar-benar bermakna, melainkan sekadar kosmetik. Joget pejabat tidak menandakan kebebasan, melainkan kepatuhan pada tuntutan citra. Mereka menari bukan karena harap, tetapi karena takut tampak tidak sejalan. Ancaman itu tidak pernah diucapkan, tetapi semua merasakannya.
Kita menyaksikan sebuah paradoks: negara yg seolah merdeka menari, tetapi justru semakin terikat pada tuntutan panggung. Joget yg harusnya spontan malah jadi simbol keterpaksaan baru. Tubuh pejabat, yg dulunya dibekukan oleh protokol, kini dibekukan oleh kamera: ia harus bergerak dengan cara tertentu, pada momen tertentu, demi citra tertentu. Bahkan kebebasan tubuh pun kini jadi alat politik.
Pada akhirnya, kita harus jujur: semua ini hanyalah candaan yg terlampau serius. Tidak ada senjata di balik panggung, tidak ada surat pemecatan bagi pejabat yg enggan bergoyang. Ancaman itu semu, sekadar bayangan dari ketakutan untuk terlihat kaku. Joget di istana hanyalah permainan citra, hiburan yg dipoles jadi ritual kenegaraan. Ia menggelitik sekaligus menyedihkan, jenaka sekaligus getir. Dan kalau suatu hari nanti sejarah menuliskan bab ini, barangkali akan tertulis; bangsa yg lahir dari revolusi & darah akhirnya memilih untuk merayakan dirinya sendiri dengan pinggul para pejabat yg bergoyang. Sebuah tragedi yg dikemas dalam tawa, sebuah lelucon yg diceritakan dengan paras serius.



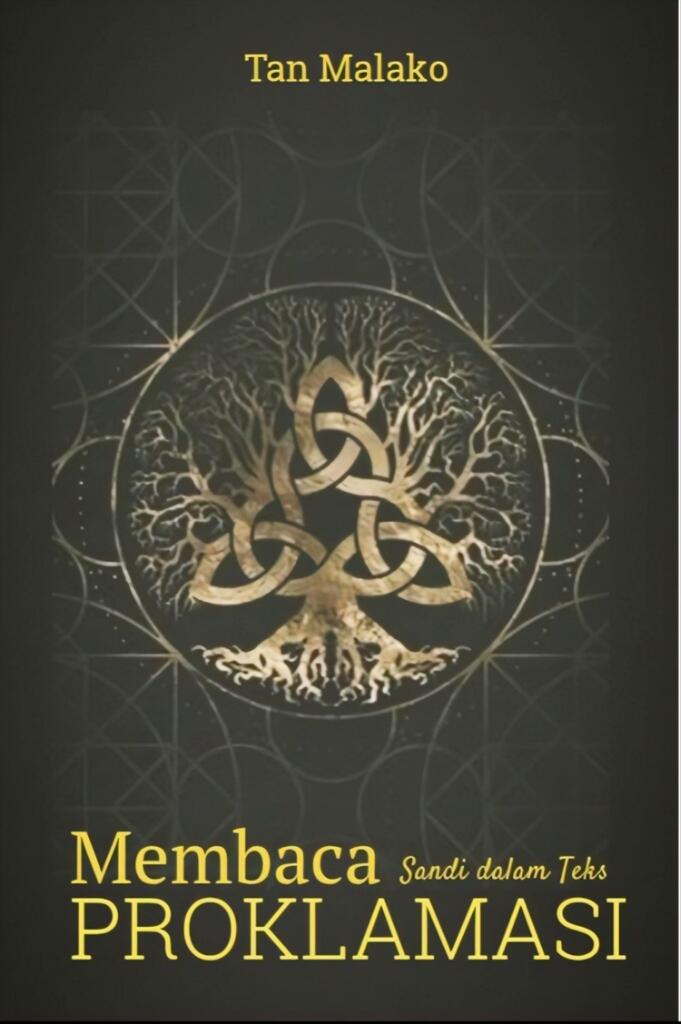



![[HOT ISSUE] Pajak Tanah Naik 4001000%, Warga Menjerit!](https://wgnewss.com/wp-content/themes/newscrunch/assets/images/no-preview.jpg)