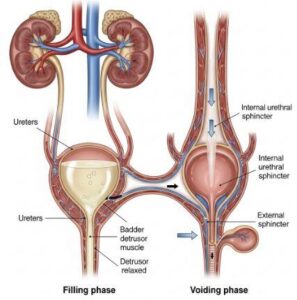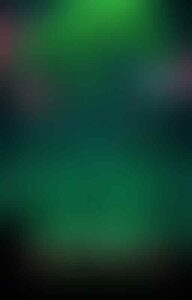Warung Kopi Tengah Hujan
Langit sore itu kelabu. Awan menggantung berat seperti beban perasaan yg tak kunjung terhinggakan. Hujan turun perlahan, seperti rintik air mata yg malu-malu menuruni pipi. Di pinggiran kota kecil bernama Banyu Asih, berdirilah sebuah warung kopi sederhana beratap seng & berdinding kayu. Warung itu bernama **Warung Kopi Tengah Hujan**, meskipun sebenarnya tidak sering hujan ketika orang-orang datang ke sana. Nama itu diberikan oleh pemiliknya sendiri, Pak Darso, karena katanya warung itu paling ramai justru saat hujan turun.
Pak Darso bukan lelaki biasa. Ia pendiam, tetapi hangat. Umurnya sudah hampir kepala enam, dengan rambut yg beberapa akbar sudah memutih. Ia punya satu kebiasaan unik: setiap pelanggan yg datang, akan ia sajikan kopi tanpa bertanya harap kopi apa. Aneh? Mungkin. Tapi yg lebih aneh, hampir semua pelanggan merasa kopi itu adalah kopi yg mereka butuhkan.
Suatu sore, saat hujan turun perlahan seperti biasa, datang seorang pemuda dengan ransel lusuh & mata sembab. Namanya Raka. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya di kota. Tak ada tempat untuk pulang, & tak ada tujuan untuk dilangkahkan. Ia berhenti di warung itu karena harap berteduh, tetapi malah disambut dengan senyuman tulus & secangkir kopi panas.
Silakan duduk, Nak. Di sini, semua yg datang karena hujan, sering menemukan sesuatu, mengatakan Pak Darso sambil tersenyum.
Raka cuma mengangguk. Tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi. Hangatnya mengalir dari jari hingga ke dada. Rasanya pahit, tetapi ada manis tipis di akhir tegukan. Seperti asa kecil yg nyaris padam.
Namanya siapa? tanya Pak Darso pelan.
Raka, Pak.
Hidup sedang tidak ramah, ya?
Raka mengangguk pelan, lalu menunduk. Ia tak tahu kenapa dapat menangis cuma karena pertanyaan sederhana itu. Pak Darso tidak menanyakan lebih. Ia cuma menepuk pelan bahu Raka, lalu duduk di bangkunya sendiri, memandangi hujan yg kian deras.
Beberapa saat kemudian, datang seorang wanita muda, berpayung biru, wajahnya tampak gelisah. Ia duduk di pojok, tak jauh dari Raka. Namanya Mira. Ia sedang menunggu kabar dari ayahnya yg dirawat di rumah sakit. Ia harap menenangkan diri sejenak, & entah mengapa kakinya membawa dirinya ke warung itu.
Pak Darso menyajikan kopi untuk Mira tanpa banyak bicara. Hanya senyum yg ia berikan, lalu kembali ke tempatnya semula. Hujan tetap turun. Tapi di dalam warung itu, waktu seakan berjalan lebih pelan. Suara tetes air di atap seng jadi musik latar dari dua jiwa yg sama-sama patah.
Tak lama, Mira & Raka saling menatap. Bukan karena jatuh sayang pada pandangan pertama, tetapi karena merasa seperti sedang bercermin. Luka mereka berbeda, tetapi rasa hancurnya sama. Mereka bicara, pelan, tanpa tujuan. Bercerita tentang kegagalan, kehilangan, & keharapan untuk berhenti sejenak dari dunia yg terlalu cepat berputar.
Pak Darso cuma mendengarkan dari kejauhan. Ia tidak pernah ikut campur. Tapi ia tahu, warungnya sudah jadi tempat di mana dua orang asing menemukan kembali sedikit harapan.
Malam mulai turun. Hujan pun perlahan reda. Tapi tidak dengan rasa hangat yg tertinggal di dada keduanya.
Sebelum pergi, Raka menoleh & berkata, Terima kasih, Pak. Saya datang cuma untuk berteduh tetapi rasanya seperti pulang.
Pak Darso cuma tersenyum. Kopi yg baik bukan cuma soal rasa, tetapi soal waktu kapan ia disajikan.
Raka & Mira pergi bersama. Bukan sebagai pasangan, bukan pula sebagai teman dekat. Tapi sebagai dua orang yg tahu bahwa mereka tidak sendirian. Mereka akan menjalani hari-hari sulit ke depan, tetapi setidaknya kini mereka tahu, ada tempat di dunia ini di mana hujan dapat membawa pertemuan.
Dan Warung Kopi Tengah Hujan tetap berdiri. Menyambut siapa saja yg datang karena hujan. Bukan untuk menjual kopi, tetapi untuk membagikan kehangatan.
—